Membludak.
Hanya kata itu yang bisa saya sampaikan untuk sepatu Compass.
Urban Sneaker Society tahun ini dihelat pada 8—10 November 2019. Acara yang diinisiasi oleh Sayyed Muhammad itu mengundang beberapa merek lokal untuk merilis edisi spesialnya. Tak hanya Rafheoo dan Pijak Bumi, Compass yang notabene sepatu lokal paling beken beberapa waktu belakangan juga turut berpartisipasi.
Kali ini, mereka merilis Compass Gazelle edisi spesial yang dinamai “Vintage”. Sepatu yang didesain untuk mengingat kembali sepatu bersol karet vulkanisasi era 1960-an. Tampilannya cenderung klasik. Bagian ujung depan sol (heel drag) dan tumit diberi ornamen selapis karet tambahan bermotif garis. Ada empat varian warna untuk edisi kerah tinggi (hi-cut) dan rendah (low cut) yang disajikan.
Antrian mengular di depan gerai Sepatu Compass.
Saya sempat berbincang sejenak dengan Aji Handoko Purbo selaku desainer. Profilnya sudah kami bahas di majalah Mainbasket edisi Maret 2019. Dalam wawancaranya itu, ia juga memberi pendapat tentang perkembangan sepatu lokal dewasa ini.
Ia tampak kelelahan. Di malam sebelumnya, kami sama-sama lembur. Saya mempersiapkan lapangan untuk gelaran Mainbasket 3x3 bareng DBL Play sementara Aji tampak sibuk menata gerai Compass. Lokasi kami bersebelahan sehingga bisa melihat aktivitas satu sama lain.
Keesokan harinya, kami bertemu kembali. Hari pertama USS dipilih untuk merilis Compass Gazelle “Vintage”. Setelah tampak senggang, saya menghampirinya. Niat saya sama seperti sebelumnya, yaitu berbincang tentang produk yang sudah ia besarkan namanya. Membuat konsumen mengantre adalah prestasi yang layak diceritakan.
“Mas Aji, kok tampak lesu,” sapa saya membuka obrolan. Basa-basi yang sudah lazim.
“Saya tidur hanya satu jam tadi malam, Mas. Sekarang rasanya seperti melayang,” kata Aji.
Aji tahu mau ke mana obrolan saya. “Mas, maaf ya, saya sedang tidak ingin menerima wawancara. Sudah berkali-kali saya menolak ajakan wawancara dengan media manapun tentang Compass. Kondisi yang terjadi sekarang sungguh di luar dugaan siapa saja yang melihatnya, termasuk saya,” katanya dengan nada tegas.
Baiklah. Saya lalu mengajaknya berbincang ringan saja. Tentang tema dekorasi gerai Compass di USS.
Anda pernah cukur rambut di tukang cukur tradisional yang memasang poster berjudul “Top Collection” di temboknya? Itu yang saya lihat. Rasanya seperti membuka kenangan saat diantar bapak saya memangkas rambut di tukang cukur semasa kecil. Dekorasi itu tampak begitu "Indonesia". Sajiannya dilengkapi properti pendukung mulai dari cermin, kursi salon, kain penutup, bedak merek Rita yang legendaris itu, dan kertas bertulis daftar harga. Sama sekali tidak ada aktivitas “buang sial” di sana.
Bagian dalam tampak tenang. Hanya ada satu orang konsumen yang diperbolehkan masuk untuk membeli Gazelle “Vintage” ditemani satu orang pegawai. Kondisi itu berbanding terbalik dengan yang ada di luar gerai. Antreannya sangat panjang. Mengular hingga ke gerbang depan. Padahal, letak gerai Compass berada di ujung lantai dasar. Para pemburu Compass itu datang sejak dini hari. Sebelum gerbang acara dibuka.
“Mengapa gerai Compass dibuat seperti kios tukang cukur rambut?” tanya saya.
“Seperti slogan yang sudah digaungkan. Compass itu sepatu asli Indonesia. Jadi, saya ingin menampilkan dekorasi gerai yang sangat Indonesia. Maka, tercetuslah ide untuk menyulapnya seperti suasana kios tukang cukur rambut,” katanya. Apa yang ditampilkan senada dengan konsep klasik dari sepatu yang dijual. Termasuk warnanya.
“Tunggu, apa hubungannya sepatu dan kios tukang cukur?” tanya saya dalam hati.
Aji dapat membaca ekspresi bingung saya. Ia pun menjelaskannya sesaat kemudian.
“Ke depan, saya ingin membawa Compass dengan konsep seperti ini ke kota lain. Mengapa dibuat seperti itu? Agar konsumen sendiri yang menafsirkannya. Intinya, saya ingin sepatu Compass kaya akan cerita. Cerita itu datang dari pengalaman yang dialami siapa saja. Bayangkan berapa banyak cerita yang muncul andai setiap pemakai Compass punya cerita sendiri-sendiri?” kata pria kelahiran Jakarta ini.
Ekspresinya kini tampak lebih baik dari saat saya mulai menyapanya beberapa menit lalu.
Aji menegaskan kembali bahwa ia kaget dengan animo masyarakat yang sangat besar. “Ini bukan edisi kolaborasi, bukan pula versi yang diproduksi langka. Saya menganggapnya adalah rilisan spesial. Kami memproduksinya 1000 pasang. Namun, lihatlah semangat ini. Saya sudah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikannya.”
“Setidaknya, mereka yang sudah antre punya cerita masing-masing tentang Compass. Entah tentang produknya, suasana gerainya, cara mendapatkannya, apa pun. Terserah mereka mau memaknainya seperti apa, dan itulah yang justru saya cari. Dinamika pengalaman merekalah yang menjadikan Compass tidak sekadar sepatu,” pungkasnya.
Perbincangan kami semakin seru saat Bram Nein datang. Bram Nein adalah kolektor adidas Campus 80’s terbesar di Indonesia. Jumlah sepatunya ada ratusan pasang. Di kancah kolektor sepatu adidas, Bram adalah sosok yang dihormati. Kesukaannya pada adidas sudah membawanya dalam sebuah perjalanan kunjungan ke kantor pusat adidas di Herzognaurah, Jerman. Tak banyak orang punya privilese seperti itu.
“Gila, bisa seperti ini antrenya!” kata Bram sekaligus menyapa kami berdua.
“Ya, begitulah. Target kami untuk menghabiskan Gazelle 'Vintage’ hari ini (8 November 2019). Besok rencananya, sih, menjual Gazelle klasik yang biasa kita jajakan,” balas Aji. Mereka pun bercengkerama layaknya kawan yang lama tak bersua.
Saya tidak ikut mereka yang berlomba membeli Compass Gazelle “Vintage” hari ini. Akan tetapi, saya punya cerita versi saya tentang Compass. Cerita itu baru saja Anda baca. Sebuah sepatu yang begitu diminati, tetapi Sang desainernya tidak pernah menduga akan jadi sebesar ini.
Dunia sneaker lekat dengan pasar sekunder. Di sana, para pembeli pertama akan menjual kembali sepatu yang dicari banyak orang dengan harga lebih tinggi. Sebut saja mereka reseller. Air Jordan dan adidas Yeezy bisa dibilang sebagai sepatu bersol karet yang berlalu-lalang di forum-forum jual beli. Harganya jauh lebih tinggi dari sepatu lokal.
Tak disangka, Compass yang dibanderol ratusan ribu Rupiah itu bisa jadi bagian dari kultur tersebut. Harga jual pertama (retail) saya rasa sanggup digapai para pengunjung USS. Namun, jumlahnya yang terbatas membuatnya laris manis di luar sana.
Kini, Aji Handoko dan tim Compass punya pekerjaan rumah yang besar. Bagaimana memenuhi permintaan konsumen terhadap produk itu. Layak dinanti apakah mereka tetap dengan cara seperti ini atau memuaskan keinginan konsumen dengan meningkatkan jumlah produksi barang. Kita tunggu saja.


























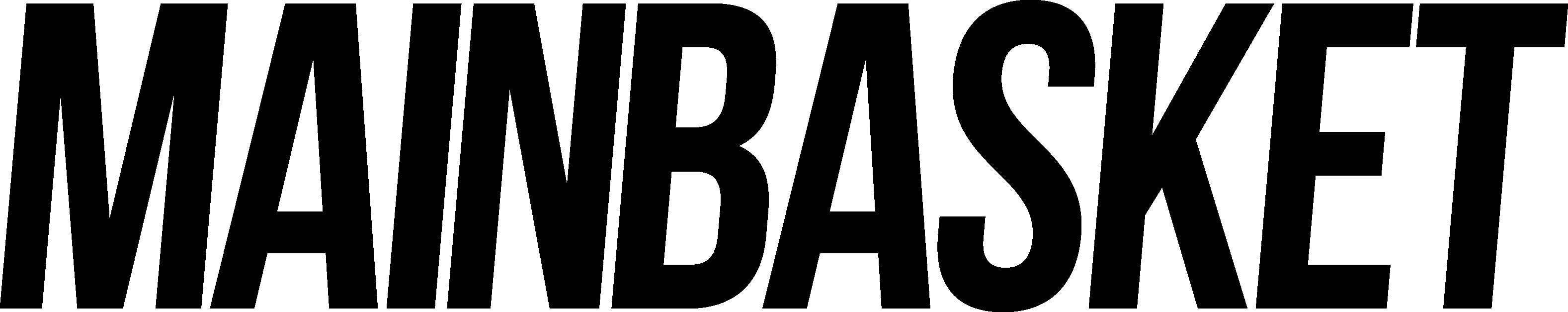




 0822 3356 3502
0822 3356 3502