“Saya lebih menyukaimu daripada keberadaan media sosialmu.”
—Ansel Elgort, aktor, via Twitter
Saya mengunggah sebuah foto di Instagram. Foto itu kemungkinan besar adalah unggahan terakhir saya di 2018. Saya melakukan itu karena merasa terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada meluangkan waktu untuk keluarga dan teman-teman. Bagaimanapun, Instagram seolah menyedot hari-hari yang seharusnya saya habiskan di “dunia nyata”.
Dewasa ini, saluran informasi memang cenderung bertambah terbuka. Hadirnya media sosial seperti Instagram dengan fitur story-nya bahkan membuat konsep jarak dan waktu relatif berubah. Keterhubungan antarmanusia pun telah didefinisikan ulang. Manusia bisa mengetahui keadaan orang lain hanya lewat media sosial dalam tempo yang nyaris singkat.
Boleh dibilang, media sosial itu mempersempit dunia. Ada perjumpaan antaridentitas sampai budaya yang sulit terelakkan. Ada banyak interaksi dalam keberagaman. Semuanya saling menyapa di ruang realitas virtual sampai-sampai manusia rasanya tidak ingin lepas dari sana. Belakangan malah muncul istilah fear of missing out (FOMO). Padahal tidak semua orang bisa menghadiri segalanya.
Kendati demikian, tetap saja, beberapa orang—kalau bukan semuanya—selalu ingin berpergian meski harus berhadapan dengan tanggung jawab. Ada kalanya orang ingin hadir di perkumpulan lingkaran pertemanannya, tetapi ia punya pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu juga. Apa daya, ia pun harus merelakan waktu berkumpul bersama teman-temannya supaya pekerjaan tidak terbengkalai. Saat itulah orang tersebut—boleh jadi—merasakan apa yang disebut FOMO.

FOMO pada dasarnya adalah perasaan cemas kehilangan sesuatu yang menarik dan atau menyenangkan di suatu tempat. Media sosial seringkali hadir untuk mengabadikan perasaan tersebut, terutama ketika—seperti kasus di atas—melihat teman-teman mengunggah kegiatan mereka tanpa kita. Perasaan itu benar-benar bisa “memakan” manusia.
Menurut penelitian perusahaan komunikasi pemasaran James Walter Thompson, FOMO bahkan berkontribusi pada ketidakpuasan orang pada kehidupan sosial mereka. Orang-orang seringkali merasa kekurangan meski kebutuhan mereka sebenarnya terpenuhi. Saya pun merasakan hal itu. Saya seringkali melihat orang lain memiliki kehidupan yang menyenangkan di media sosial mereka, sementara saya tidak bahagia dalam tiga tahun ke belakang. Ada sebuah perasaan cemas yang membuat saya pada akhirnya malah seperti disingkirkan oleh kehidupan sosial. Maka dari itu, tidak heran jika J.J. Redick, garda tembak Philadelphia 76ers, menyebutnya sebagai “a dark place” (sebuah tempat yang gelap).
“Itu bukan tempat yang sehat. Itu tidak nyata. Itu bukan tempat yang sehat untuk ego kita,” kata Redick, seperti dikutip Bleacher Report.
Bagaimanapun, media sosial punya sisi baik, tetapi tanpa sadar, sesuatu yang dianggap baik itu ternyata bisa menjelma sebaliknya. Pengalaman Redick—salah satunya—bisa menjelaskan hal itu. Karena pada suatu ketika, ia mengalami kejadian yang semakin menguatkan alasannya menghapus semua akun media sosial yang ia buat.

Redick pernah terlalu sering terpaku pada telepon genggamnya di sekitar istri dan dua putranya yang masih kecil. Secara berulang, ia memeriksa kanal-kanal berita di Business Insider, HoopsHype, dan Twitter untuk menyuapi egonya akan informasi. Ia bahkan berlangganan Basketball Reference untuk mendapatkan informasi tentang statistik NBA yang bebas iklan. Informasi itu tentu akan berguna untuknya, terutama ketika mengarungi karir di NBA. Namun, ia malah jadi lebih peduli pada telepon genggam daripada keluarganya karena terlalu menaruh perhatian kepada kanal-kanal berita yang mestinya jadi asupan positif bagi otaknya.
“Itu bahkan dilakukan tanpa sadar,” kata Redick lagi. “Saya harus mengakui, setiap kali kita berada di lampu merah dan telepon genggam kita ada di dekat kita, kita pasti mengambilnya. Itu terjadi begitu saja. Bahkan ketika kita menaruh telepon genggam dan keluar ruangan, kita selalu tahu di mana barangnya berada. Itu menjadi bagian dari diri kita. Itu sangat mengerikan.”
Perasaan Redick tentang media sosial itu—saya pikir—dirasakan banyak orang di dunia. Beberapa selebritas pun ada yang pernah mengistirahatkan akun media sosialnya. Kanye West, selebritas berkebangsaan Amerika Serikat, misalnya, sempat meninggalkan Twitter pada 2012 karena kurang tidur dan kelelahan. Jika ia tidak melakukan itu, ada kemungkinan media sosial malah menyedot waktunya lebih banyak.
Sayangnya, tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang mau dan bisa beristirahat dari media sosial.
Suatu ketika, sekitar dua-tiga tahun lalu (saya lupa tepatnya tahun berapa), seorang atlet basket Indonesia pernah mengaku tidak bisa lepas dari telepon genggamnya barang sehari pun. Ia harus selalu membawa telepon genggamnya ke mana pun ia pergi. Hal itu bisa jadi berbahaya karena beberapa orang di luar sana justru tidak bisa lepas dari media sosial karena mengalami FOMO yang parah.

Eric Baker, penulis buku Barking Up the Wrong Tree, pernah menulis di TIME bahwa penelitian menyebutkan, orang-orang dengan FOMO berhenti memperhatikan kehidupan dan beralih ke media sosial untuk menyembuhkan kebahagiaan mereka. Meski dimaknai dalam sudut pandang yang berbeda-beda, pada titik ini, FOMO pun jadi terdengar seperti sebuah puisi Po Chu-I dalam buku The Year of Living Dangerously:
…
Semenjak kita berpisah, kita telah sama-sama menua;
Dan pikiran kita direcoki banyak kecemasan;
Namun bahkan sekarang aku membayangkan telingaku penuh
Dengan suara giok bergemerincing di tali kekangmu.
Ibaratkan pusi di atas, media sosial itu seperti suara giok bergemerincing di tali kekang yang memenuhi telinga. Media sosial bisa jadi suara-suara yang bergumam di dalam kepala dan menebar kecemasan seandainya kita tidak tahu cara beristirahat darinya. Oleh karena itu, saya pikir keputusan Redick, Kanye, dan para pesohor lainnya yang pernah mematikan media sosial mereka—entah sejenak atau selamanya—terasa benar.
Bagaimanapun, kita memang perlu menjaga kewarasan kita dengan beristirahat. Psikolog Nick Hobson di Psychology Today bahkan menganjurkan orang untuk mengurangi FOMO dengan mengurangi fokus akan rasa kehilangan dan mulai memperhatikan apa yang benar-benar kita lakukan. Pada akhirnya, ketika cemas, kita perlu berdamai dan menghadapi realitas itu sendiri.
Foto: NBA



























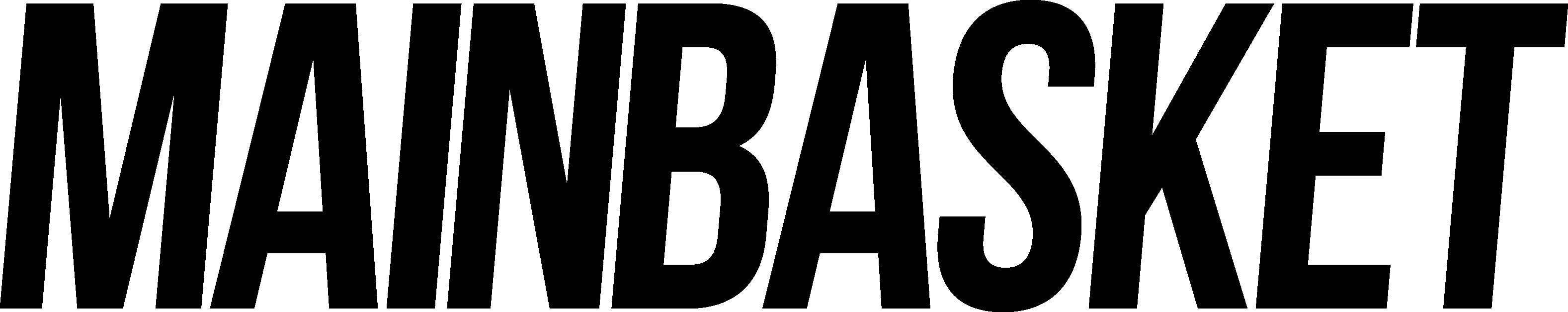




 0822 3356 3502
0822 3356 3502