Menapak Jejak Pebasket Afro-Amerika dalam Peringatan Black History Month
Introduksi
Amerika Serikat memiliki sejarah panjang yang melibatkan warga keturunan Afro-Amerika dalam kisahnya. Pada Februari setiap tahunnya, Amerika Serikat memperingati Black History Month untuk mengingat kembali tokoh-tokoh dan momen besar orang-orang kulit hitam. Upaya itu dilakukan untuk mengingatkan kembali betapa panjang dan hebat perjuangan mereka dalam persoalan kesetaraan ras dan hak asasi manusia.
Tidak terkecuali NBA, liga bola basket paling terkenal seantero dunia itu juga ikut memperingatinya. Elemen-elemen penting dalam sejarah Afro-Amerika seringkali tampil di saat-saat ini, entah lewat pernak-pernik seperti kaus maupun sepatu. Para pemainnya tampak hadir dengan semangat yang sama: pelajaran tentang kesetaraan (equality).
Dengan semangat itu, Mainbasket menggali kisah-kisah pemain keturunan Afrika dan menghadirkannya dalam enam tulisan. Kami mendefinisikan semangat kesetaraan secara luas untuk memaknai kisah-kisah inspiratif dari para pemain NBA keturunan Afrika.
Sebagai pengawal kisah-kisah tersebut, kami menghadirkan terlebih dahulu sebuah cerita yang berasal dari Kongo. Kami mengangkat sejarah hidup Serge Ibaka, forward Toronto Raptors, yang berangkat dari Perang Kongo Kedua sampai ke Spanyol, hanya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Meski ia bukan seorang Afro-Amerika (Ibaka berstatus warga negara Spanyol), kisah hidupnya yang inspiratif rasanya layak untuk diketahui orang banyak.
***
“Hanya orang mati yang melihat perang berakhir.”
— Plato
Terlepas dari kontroversi tentang siapa yang mengatakan kalimat di atas, Ridley Scott, sutradara Black Hawk Down, memilih kutipan itu sebagai pembuka filmnya berdasarkan seorang ahli dari Perancis. Dan bagi masyarakat Kongo, rasanya hal itu benar adanya. Bagaimana tidak, dua kali mereka mengalami perang yang cukup panjang, membuat mereka menjadi pengungsi di tanah sendiri hingga mesti mencari suaka ke luar negeri. Bagi mereka yang sempat berada di tengah-tengah kondisi Perang Kongo Kedua, misalnya, pilihan untuk pergi ke tempat lain adalah sebuah keharusan.
Serge Kanyamuhanga, seorang warga Republik Demokratik Kongo, baru setengah jalan menuju sekolahnya ketika suara tembakan meletup di antara bangunan yang ia lewati. Semua orang panik dan berusaha melepaskan diri dari situasi berbahaya itu. Kanyamuhanga berlari di antara hingar bingar untuk mencari adiknya yang berusia 12 tahun. Enam belas tahun berlalu, ia masih ingat betul kejadiannya.
“Tidak ada jalan untuk kabur, di mana-mana ada tentara. Anak-anak diculik dan guru-guru ditangkap. Kami dibawa ke sebuah kamp dan merasa sangat takut karena kami tahu kami dibawa untuk dijadikan tentara. Kami diajari untuk mengangkat senjata, menembak, dan melawan tentara Kongo,” jelas Kanyamuhanga, seperti diceritakan Sorcha Pollak, The Irish Times.
Kini Kanyamuhanga tengah tinggal di Irlandia, membangun hidup barunya setelah berhasil keluar dari perang pada 2013. Saat itu, ia menelusuri jalan keluar dari Afrika—lewat Uganda—untuk sampai ke Eropa. Maka tibalah ia di negeri para Irish.
Di tanah yang sama, Serge Ibaka, forward Toronto Raptors, juga mengalami hal serupa. Sebelum sampai ke tanah para matador, Ibaka lahir di Brazzaville, Republik Kongo, dari pasangan pemain bola basket yang memiliki 18 anak. Ibaka merupakan anak ke-15.
Ketika itu, orangtua Ibaka membela dua negara berbeda. Ayahnya, Desire Ibaka, bermain untuk tim nasional Republik Kongo sementara ibunya, Amadou Djonga, membela Republik Demokratik Kongo. Kedua orang itulah akar rumput yang menjawab pertanyaan tentang dari mana Ibaka menumbuhkan bakat olahraganya.
Ibaka mengenal basket sejak usia 7 tahun. Di usia itu, ia sudah bermain basket di jalanan Kota Brazzaville, sebuah kota yang ukurannya tak lebih besar dari Toronto, tempat ia bermain profesional belakangan ini. Ia menghabiskan waktunya di sekolah maupun ketika senggang untuk bermain basket dengan teman-temannya di sana, di jalanan-jalanan Kota Brazzaville.
“Saya bermain setiap hari,” kenang Ibaka, seperti dinukil dari situs berita NewsOK. “Jika satu hari saja saya tidak bermain, rasanya kesal, seperti saya kehilangan sesuatu hari itu.

Serge Ibaka bersama keluarganya di Kongo, Afrika. Foto: AP
Di Kongo, Ibaka bermain dengan fasilitas seadanya. Tidak ada yang sempurna di sana. Tidak seperti di Amerika Serikat. Lapangan berlubang, papan kayu yang reyot, dan sepatu-sepatu yang tampak sedikit rusak dengan bolong di mana-mana, menjadi pemandangan lumrah yang mesti dimaklumi. Namun, Ibaka dan teman-temannya tidak peduli dan terus bermain.
“Basket adalah sesuatu yang sangat kami cintai. Kami tidak peduli dengan bagaimana kami memainkannya, yang penting kami bisa bermain,” kata Ibaka lagi.
Namun, basket tidak serta merta mengubah hidupnya. Peranglah yang benar-benar mengubah kehidupan. Ibaka dan keluarganya harus mengungsi lantaran perang benar-benar tak memberikan mereka harapan hidup yang layak. Apalagi ketika ia harus kehilangan ibunya di usia 8 tahun. Ia pun jadi semakin dekat dengan keluarganya, terutama dengan ayahnya. Keluarga adalah satu-satunya sumber kasih sayang ketika ia tumbuh di tengah kekacauan.
Ketika Perang Kongo Kedua—perang terbesar dalam sejarah Afrika—pecah untuk kali pertama pada 1998, Ibaka dan keluarga mengungsi ke kota yang lebih kecil di Ouesso. Ia tinggal di sana selama empat tahun, hidup hampir tanpa listrik dan kesulitan air, hingga ayahnya memutuskan untuk kembali ke Brazzaville pada 2002.
Malang tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih, Desire kembali ke pelabuhan untuk mendapatkan pekerjaan lamanya di perbatasan negara tetangga, Republik Demokratik Kongo, tapi pekerjaan itu ternyata membuatnya berakhir di penjara. Ia berada di wilayah yang salah ketika bekerja dan menjadi tahanan politik selama setahun, sampai perang "berakhir" pada 2003.
Selama Desire ditahan, Ibaka tingga lbersama neneknya di kota. Ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri tanpa kehadiran orangtua, hanya nenek dan sanak saudaranya. Menurut Pele Gallego, agennya di Spanyol, itulah mungkin yang membuat Ibaka kuat secara mental. Ia pun tumbuh semakin kuat dengan berlatih basket hampir setiap hari. Ia bergabung dengan klub basket lokal yang fokus pada pengembangan pemain muda, Avenir du Rail. Dalam asuhan Pelatih Maxim Mbochi—yang sekaligus bekas rekan setim ayahnya—Ibaka memperkuat fundamental.
Dalam sebuah tulisan di The Players’ Tribune, Ibaka menceritakan betapa cinta kepada basket itu tumbuh dengan baik. Ia semakin menyukai olahraga permainan tersebut. Ia bilang, Tuhan agaknya memang menciptakannya untuk bermain basket. Ia mengetahui itu ketika suatu kesempatan bermain di sebuah turnamen datang, meski baginya, kemungkinan mengikuti turnamen itu sangatlah kecil.
Tidak ada dalam sejarahnyanya tim nasional U-15 bisa terbang ke luar Afrika hanya untuk mengikuti sebuah turnamen. Tidak ada biayanya. Namun, pada akhirnya ternyata mereka bisa terbang untuk mengikuti turnamen itu. “Itu kesempatan sekali seumur hidup,” katanya, tapi Ibaka sama sekali tidak punya bayangan tentang turnamen itu. Ia buta kekuatan lawan.
Kendati begitu, Ibaka tahunya bisa bermain bagus melawan tim-tim yang menurutnya lebih baik, seperti Nigeria dan Angola. Kedua negara itu sering mengirim timnya ke Eropa untuk mengikuti pertandingan dengan kompetisi yang ketat. Namun, ketika melawan Afrika Selatan, misalnya, Ibaka mampu bermain baik dengan mengemas tripel-dobel 27 poin, 19 rebound, dan 12 blok dan berhasil keluar sebagai pemain terbaik.
Turnamen itu, kesempatan itu, mengubah hidupnya. Sejak itu ia pun mulai bermimpi bisa bermain di luar negeri, terutama Amerika Serikat di mana ada NBA di sana.
“Saya bermain keras dan sangat fokus pada pertandingan sampai saya tidak menyadari bahwa bisa saja ada pencari bakat profesional di Afrika Selatan. Penampilan saya waktu itu murni karena saya menikmatinya,” tulis Ibaka dalam esainya di situs The Players’ Tribune.
Ibaka baru berusia 17 tahun ketika ia meninggalkan keluarganya untuk menyongsong hidup baru. Ia terbang ke Perancis dan tinggal di sana beberapa waktu, sebelum akhirnya hijrah ke Spanyol. Baginya, ini perjalanan paling sulit dalam hidupnya karena ia harus meninggalkan keluarganya jauh sekali. Apalagi ia tidak bisa bahasa Spanyol.
Seperti juga Kanyamuhanga, pria di awal tulisan ini yang terbang ke Irlandia untuk mengubah hidupnya, Ibaka punya pandangan yang sama. Ia benar-benar yakin Kongo tak cukup besar untuk menumbuhkan bakatnya ke tingkat yang lebih jauh. Oleh karena itu, ia pun hijrah ke Eropa demi mendapat pelajaran yang lebih baik.
Di Spanyol, Ibaka membangun namanya. Sedikit demi sedikit ia belajar dan mengasah bahasa setempat sambil bermain di divisi dua Spanyol, L’Hospitalet DKV Joventut. Ia pun sempat mengikut beberapa gelaran yang berhubungan NBA. Para pencari bakat pun mulai dapat mengendus kehadirannya. Ibaka masuk ke radar NBA.
“Kemampuan atletik dan energi Serge menggugah kami,” ujar Sam Presti, manajer umum Oklahoma City Thunder, tim pertama Ibaka di NBA, seperti dilansir NewsOK.

Serge Ibaka ketika bermain untuk tim pertamanya di NBA, Oklahoma City Thunder. Foto: AP
Thunder memang tertarik meminang Ibaka lewat NBA Draft. Mereka pun mengirim pemandu bakat untuk melihat potensi Ibaka yang saat itu bermain di ACB League, Spanyol. Mereka menimbang kemampuan individunya di basket hingga kemampuan komunikasinya, karena tim-tim NBA tahu, kemampuan basket saja tidak cukup membuat mereka bertahan secara tim. Mereka membutuhkan pemain yang juga dapat berkomunikasi dengan baik dan bermain secara kolektif.
“Kami menghimpun segala informasi yang bisa kami kumpulkan,” jelas Presti lebih lanjut, “tentang fokusnya, etos kerjanya dan dari mana ia berasal, ia datang dari mana dan apa yang membuatnya cocok dengan kami.”
Presti dan Thunder akhirnya memilih Ibaka di urutan ke-24 pada NBA Draft 2008. Namun, pemain asal Kongo itu tidak serta merta langsung bisa bermain di NBA. Thunder memutuskan untuk menunda keberangkatan Ibaka dan membuatnya tetap di Eropa.
Juli 2009, menjadi tahun besar bagi Ibaka. Thunder akhirnya memboyong Ibaka ke Amerika Serikat. Ia meneken kontrak dua tahun dengan tim asal Oklahoma tersebut. Itulah momen besar dalam hidupnya yang membuat ia hingga kini bertahan di NBA. Selama karirnya, ia terkenal sebagai pemain kuat yang berani beradu fisik di bawah ring, terutama ketika bertahan. Ibaka, sesuai catatan NBA, pernah masuk ke jajaran elit All-Defensive First Team sebanyak tiga kali dan memimpin perolehan blok dua musim berturut-turut (2012-2013).

Serge Ibaka kini membela Toronto Raptors, memperpanjang kontraknya tiga tahun seharga AS$65 juta pada 2017 lalu. Foto: Sports Illustrated
Ibaka sempat kembali ke Eropa ketika NBA mengalami hiatus (lockout season) pada 2011. Ia bergabung dengan Real Madrid yang berlaga di EuroLeague sampai lockout berakhir. Di tahun yang sama, Ibaka memperoleh kewarganegaraan Spanyol dan berhak membela tim nasional. Untuk pertama kali, ia tampil di gelaran Eurobasket 2011 dan memenangkan medali emas setelah menumbangkan Perancis 98-85.
Tidak sampai di situ, Ibaka juga ambil bagian ketika Spanyol meraih medali perak di Olimpiade London pada 2012. Saat itu timnya tidak bisa lepas dari kedigdayaan tim nasional Amerika Serikat yang bertabur bintang NBA. Akan tetapi, bagaimanapun upaya Ibaka sejauh ini akhirnya membuahkan hasil positif.
Jika mengingat jejak langkahnya dari Kongo, Ibaka memiliki perjalanan panjang yang membuatnya berada dalam radar masyarakat dunia. Anak kecil yang dulu bermain di jalanan Kota Brazzaville itu kini telah tumbuh sebagai pemain yang lebih kuat. Ia pergi dari tanah airnya, merantau ke kota-kota di belahan dunia lain, singgah di negara-negara yang memberi harapan, ia pun sampai ke tempat yang pernah ia impikan ketika kecil: NBA.
Sejak Thunder meminangnya, Ibaka telah berlabuh dari tim ke tim lainnya; ke Orlando Magic sampai akhirnya menetap di Toronto, Ontario, Kanada, untuk membela Raptors dengan kontrak baru selama tiga tahun seharga AS$65 juta. Seperti kata Kanyamuhanga, tokoh di awal tulisan ini, pergi dari Kongo adalah hal paling tepat untuk mengubah kehidupan agar lebih baik, dan Ibaka berhasil melakukannya. Ia telah sampai ke Amerika Serikat, negara yang punya sejarah panjang dan besar tentang kehidupan warga keturunan Afrika, dan berhasil bertahan di sana bertahun-tahun. Orang-orang sepertinya punya semangat juang yang sama dengan tokoh-tokoh dan momen-momen penting dalam peringatan sejarah Black History Month.
Foto: NBA
Baca juga seri Black History Month lainnya:
Menapak Jejak Pebasket Afro-Amerika dalam peringatan Black History Month
Perang Membuat Serge Ibaka Menjadi Seorang Spanyol (1/6 Black History Month)
Earl Lloyd, Sang Pionir Kulit Hitam di Laga NBA (2/6 Black History Month)
Bill Russell, Pelatih Kulit Hitam Pertama di NBA (3/6 Black History Month)
Amerika Serikat, Taksi, dan Mimpi Frank Ntilikina (4/6 Black History Month)
Texas Western Mengubah Wajah Basket Amerika Serikat (Black History Month 5/6)



























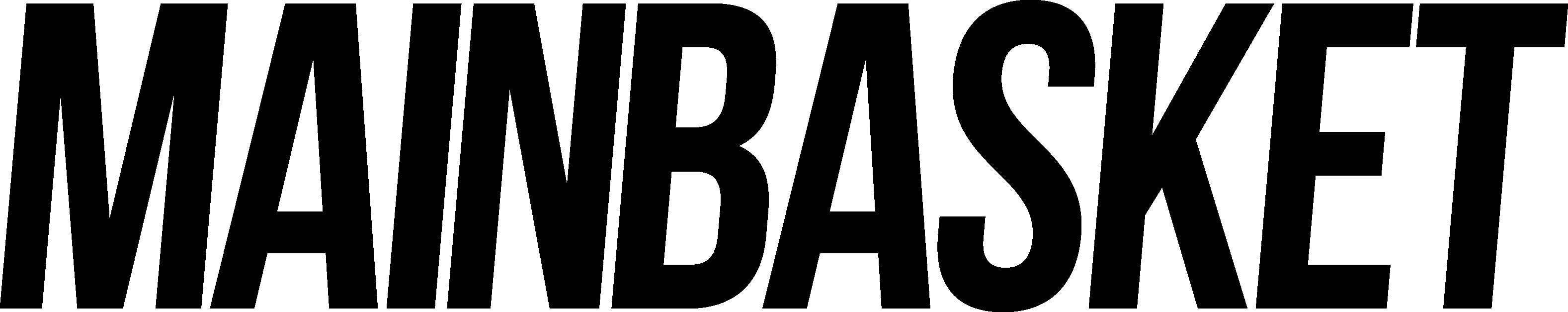




 0822 3356 3502
0822 3356 3502