“Gusti Allah ora sare.”
Begitulah kawan saya, Wanggi Hoediyatno, seorang seniman pantomim dan aktivis, menjawab ketika ditanya mengapa ia tidak “istirahat sejenak” dari perjuangannya. Karena Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat perjuangannya, dan ia merasa harus terus “bersuara”, sebab bungkam bukanlah sebuah opsi. Maka, lewat Aksi Kamisan di Bandung, ia dan teman-temannya terus berdiri menggenggam payung hitam di setiap Kamis sore. Salah satunya untuk “bersuara” supaya orang-orang menolak lupa pada tragedi-tregedi kemanusiaan di negeri ini.
Nun jauh di sana, menyeberangi Samudra Pasifik, seorang atlet bola basket juga melakukan hal yang sama. Stephen Curry, guard Golden State Warriors, menolak bungkam atas isu-isu sosial. Ia mengatakan dalam sebuah tulisan di The Players’ Tribune, “Pada 2017, di Amerika, bungkam bukan lagi sebuah opsi.”
Suatu hari, Curry dan istrinya bertemu dengan seorang veteran dari kalangan militer di sebuah restoran. Sang Veteran mendekati mereka dan mulai berbicara. Dalam obrolan itu, Curry menggarisbawahi beberapa hal, di antaranya adalah persoalan hidup veteran. Karena ternyata sebagian dari mereka hidup sulit tanpa rumah, tanpa pekerjaan, mengalami gangguan kesehatan mental, dan tentu saja kesenjangan rasial.
Di waktu lain, saya melihat Curry—lewat media-media luar negeri—menolak undangan Presiden Donald Trump ke White House. Penolakan itu berujung pada “pertengkaran kecil” di media sosial. Sebagian orang bilang apa yang dilakukan Curry sebagai sikap tidak hormat, tetapi sebagian lain memahami untuk apa ia melakukan itu. Karena sikap tidak menghormati dengan apa yang ia lakukan adalah hal berbeda. Kita bisa tahu hanya dengan melihatnya. Atau membaca sendiri apa yang dikatakan Curry lewat tulisannya di The Players’ Tribune.
Hal-hal di atas kemudian membuka mata Curry untuk bicara lebih vokal lagi. Ia sadar bahwa masih banyak orang di sekitarnya justru tidak mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Ia tahu untuk apa ia berdiri. Ia tahu untuk apa ia melawan. Sebagai tokoh masyarakat dunia, ia ingin mengatakan bahwa semua orang patut bicara dan memperjuangkan sesuatu.

Saya juga membaca kisah Ray Allen. Pensiunan NBA itu pergi ke Auschwitz untuk mengunjungi sebuah rumah tempat Nazi membantai satu keluarga. Belakangan, ia menaruh perhatian untuk mempelajari sejarah pembantaian terbesar di zaman itu. Bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kita semua. Karena pembantaian tentu saja selalu menyisakan pertanyaan dalam benak masing-masing. Seperti Allen yang bertanya, “Mengapa manusia melakukan hal seperti itu kepada manusia lainnya?”
Ia pun menulis perjalanannya. Lebih seperti perjalanan spriritual bagi saya. Karena ia mengisahkan perjalanannya itu sebagai bentuk keresahan terhadap tragedi kemanusiaan. Secara mendasar ia menulis dengan harapan tidak ada lagi tragedi serupa. Ia tidak ingin membiarkan ketidakpedulian dan pendek akal menjadi bagian dirinya, juga masyarakat dunia. Karena memang tidak ada gunanya.
Sayangnya, tidak semua mengerti. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Allen membuka media sosial dan heran melihat orang-orang tidak suka terhadap aktivitasnya yang menaruh perhatian pada tragedi masa lalu itu.
Di suatu waktu lainnya, saya mengobrol dengan Adhi Pratama (Pelita Jaya Jakarta) tentang rencana membentuk sebuah komunitas bola basket di Depok. Komunitas itu bernama Depok Nation. Ia bersama Airlangga Sabara (Hangtuah Sumatera Selatan) dan Audy Bagastyo (Satria Muda Jakarta) membentuk komunitas karena miris melihat perkembangan bola basket di kota mereka. Adhi curhat bahwa di Depok wadah anak-anak untuk bermain bola basket dengan benar sangat kurang. Alasan itu pula yang melatarbelakangi tagar #DepokButuhGORBasket di media sosial menyeruak sejak lama.
Bagi saya, upaya Adhi dkk. itu sama seperti suara Wanggi, Curry, dan Allen. Mereka sama-sama ingin berdiri memperjuangkan alasannya masing-masing. Gusti Allah ora sare. Tuhan melihat tindakan kita, baik maupun buruk. Maka, sebagai pribadi yang dikenal masyarakat luas, tidak ada salahnya mereka menggunakan ketenaran untuk menyuarakan harapan-harapan. Karena harapan mereka, jika dilihat dari ceritanya, sebenarnya kumpulan dari harapan banyak orang.
Saya jadi ingat dalam suatu kesempatan pada Agustus 2017 lalu. Saat itu di depan saya duduk seorang pengamat sepak bola, Tommy Welly. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan Bung Towel.
Dalam obrolan itu, ia mengatakan bahwa setiap olahraga selalu membutuhkan sosok supaya olahraga itu terkenal. Kata-kata itu melekat dalam kepala saya sampai hari ini, bahkan mungkin di hari-hari depan. Karena ternyata hal itu tidak hanya berlaku dalam olahraga saja. Setiap cerita membutuhkan sosok agar isinya dikenang, bahkan diperjuangkan kembali. Sama seperti apa yang dilakukan nama-nama di awal tadi.
Dengan demikian, bersuaralah apapun mediumnya. Bersuaralah dengan baik, sebab perjuangan harus tanpa henti. Apalagi dengan ketenaran-ketenaran itu. Dan, alangkah lebih baik jika memanfaatkan ketenaran untuk hal-hal baik. Dunia memang semakin jahat, tetapi kita harus lebih kuat dengan semangat itu. Suatu hari kegigihan kita sendiri yang akan memetik buahnya. Kita menanam, kita menuai.
Foto: The Players' Tribune, Sports Illustrated



























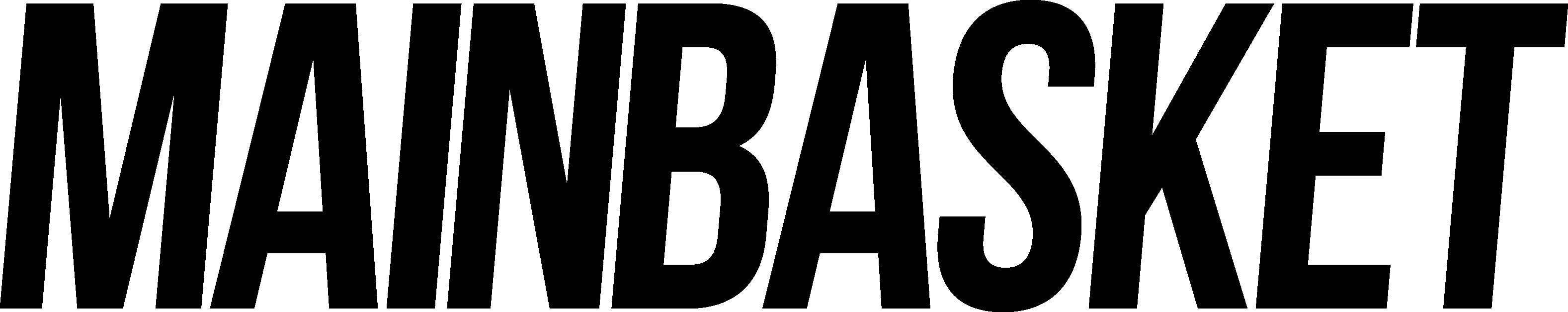




 0822 3356 3502
0822 3356 3502