Layaknya seni, olahraga kerap disebut sebagai bahasa universal. Tidak ada kendala bahasa meski Anda dari Indonesia, Argentina, Nigeria, Arab Saudi, Amerika Serikat, Jepang, atau Selandia Baru. Dalam sepak bola, mau Anda menyebutnya gol, golazo, goal, dan sebagainya, Anda dan semua orang yang melihat pertandingan itu tahu bahwa itu adalah sebuah gol. Begitu pula di basket, meski Anda dari Timbuktu, Anda tahu bola yang masuk ke ring berarti poin untuk tim yang memasukkannya (entah begitu juga di Korea Utara atau tidak).
Karena bahasanya yang universal, olahraga kerap digunakan sebagai obat dari segala macam permasalahan dunia, utamanya pertikaian. Seperti di Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta-Palembang lalu. Simbol perdamaian Korea Selatan dan Korea Utara dimunculkan dalam skuad tim putri mereka yang menggunakan nama Korea Bersatu (Unified Korea).
Saya yang cukup beruntung dapat kesempatan meliput gelaran tersebut cukup dibuat kebingungan saat melihat salah satu media politik dan ekonomi ikut nimbrung di door stop tim Korea Bersatu. Ya, saya melihat tanda pengenalnya dan jelas sekali bukanlah sebuah media olahraga. Pertanyaan yang ia lontarkan ke Kim Han-Byul pun tidak ada hubungannya dengan pertandingan sama sekali.
“Bagaimana koneksi kalian (pemain asal Korea Selatan) dengan tiga pemain dari Korea Utara? Apakah kalian membicarakan perdamaian ini selama kalian bersama? Atau justru tak membicarakannya sama sekali?” Begitu pertanyaannya.
Saya masih ingat betul karena wartawan tersebut ada persis di belakang saya dan saya cukup kaget mendengar pertanyaan itu.
Meski belakangan kedua negara tersebut dikabarkan kembali tidak akur, setidaknya mereka pernah membuktikan bahwa olahraga bisa menyingkirkan sedikit saja permasalahan “duniawi” mereka. Atau bisa dibilang, meski tidak akur secara negara, mereka tidak akan membawa masalah itu ke ranah olahraga. Korea Bersatu sendiri pulang dengan medali perak di Asian Games 2018 usai takluk dari Cina di partai puncak.
Namum, saya cukup gusar dengan kondisi dunia terkini, di tengah pandemi ini. Untuk pertama kalinya dalam hampir 26 tahun hidup saya, saya tak melihat olahraga bisa menyelesaikan masalah dunia. Sejak Maret lalu, hampir semua liga atau acara olahraga di seluruh belahan dunia terhenti, baik sementara atau berhenti total pada akhirnya.
Dalam prosesnya, negara-negara dengan penyebaran kasus yang berhasil turun mulai memperbolehkan lagi aktivitas olahraga profesional mereka. Pun demikian, aturan kesehatan terbaru yang digunakan cukup menyulitkan dan hampir semuanya (jika tidak semuanya) mengharamkan kehadiran penonton.
Ambil contoh Bundesliga Jerman yang sudah melanjutkan kembali liga mereka 16 Mei lalu. Selebrasi dalam sepak bola adalah hal yang sangat lumrah bahkan cenderung wajib saat mencetak gol. Selebrasi biasanya dilakukan beramai-ramai dan berujung aksi saling peluk antarpemain. Kini, usai gol, mereka menunjukkan gesture kebingungan. Ingin berpelukan tapi kok tampaknya salah. Tak berpelukan pun rasanya ada yang kurang. Aneh, aneh sekali.
NBA pun demikian. Sejak hiatus dari 11 Maret lalu, kepastian musim 2019-2020 akan berlanjut masih sangat abu-abu. Sempat muncul laporan akan kembali mulai tanggal 31 Juli, lalu laporan selanjutnya maju satu hari, kemudian penolakan pemain, lantas dibalas penolakan dari penolakan pemain, bingung!
Yang lebih membingungkan dari semua kondisi di NBA adalah fakta bahwa ucapan-ucapan yang tersebar di media tidak ada yang salah. ESPN melaporkan, potensi kerugian NBA jika musim berhenti mencapai 2 milyar dolar AS. Kehilangan pendapatan sebesar itu akan berujung pada penentuan ruang gaji pemain musim depan. Dampak langsung ke pemain juga tertunda hingga berkurangnya pembayaran gaji mereka untuk musim ini. Melihat ini, otak kapitalis saya meyakini bahwa NBA pasti lanjut!

Lalu muncul kasus aksi kebrutalan polisi Minnesota terhadap George Floyd yang berujung aksi protes besar-besaran di berbagai belahan dunia. Aksi ini berubah dari tuntutan hukum yang pasti atas kelakuan biadab empat polisi tersebut menjadi aksi antirasisme di berbagai belahan dunia lain, masif.
Kasus ini pula yang berujung pada penolakan melanjutkan musim dari beberapa pemain NBA yang sejauh ini dikabarkan dipimpin oleh Kyrie Irving. Menurut Kyrie, NBA berpotensi menganggu atau menghilangkan sorotan atas tuntutan perubahan sistem yang dilakukan segenap masyarakat Amerika Serikat. Untuk alasan ini, Kyrie tidak salah.
NBA sebagai salah satu olahraga dengan jumlah penonton terbanyak di dunia berpotensi menutup pemberitaan dan akhirnya membuat masyarakat lupa ada masalah sosial besar di Amerika Serikat bahkan dunia. Masalah yang sudah ada selama berabad-abad yang kini sedang diusahakan untuk dimusnahkan secara sistematis.

Mantan rekan satu tim Kyrie dan bisa dibilang sosok paling berpengaruh di NBA sekarang, LeBron James, justru beranggapan sebaliknya. Dilansir The Athletic, James masih ingin melanjutkan musim dan menurutnya, kelanjutan musim NBA tidak akan menghentikannya untuk berhenti menuntut perubahan. Dua hari lalu, James dan sederet atlet serta pesohor yang memiliki garis keturunan Afrika-Amerika membuat sebuah grup yang bertujuan melindungi hak pilih warga keturunan Afrika-Amerika dalam rangkaian pemilu Amerika Serikat yang dimulai 4 November mendatang. Atas hal ini, apa yang diyakini LeBron juga tidak salah.
LeBron melihat NBA justru sebagai panggung di mana ia bisa menyampaikan aspirasinya karena jangkauan NBA yang lebih luas. Hal ini pun sudah terbukti sepanjang 17 tahun kariernya di mana ia bisa menginspirasi banyak masyarakat mulai dari Akron, tempat lahir dan tumbuh LeBron, hingga orang-orang di belahan bumi lain.
Menariknya, beberapa komentar di dunia maya sama-sama menuding baik LeBron dan Kyrie hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Bagaimana bisa? Kyrie dan LeBron adalah dua dari sembilan pemain NBA yang mendapatkan bayaran penuh, tanpa peduli musim berjalan atau tidak. Apa yang dilakukan Kyrie dianggap beberapa warganet sebagai aksi malasnya saja. Sementara LeBron dianggap ingin mengejar gelar juara keempatnya saja. Pendapat ini, juga belum terbukti salah.

Semuanya terjadi sangat cepat dalam waktu yang nyaris bersamaan dan jika ditelaah, tidak terlihat ada yang salah. Semuanya punya kepentingan dan prioritas masing-masing. NBA, Kyrie dan pemain-pemain yang menolak melanjutkan musim, LeBron beserta pemain-pemain yang siap melanjutkan musim, sama-sama memiliki sudut pandang masing-masing.
Pun demikian, pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa besar dampak kehadiran atau ketiadaan NBA nanti? Kita sudah tak melihat NBA atau pertandingan basket secara keseluruhan dalam waktu tiga bulan terakhir. Kesal, rindu, marah, sedih, tapi kita memang tak bisa berbuat apa-apa dan tampaknya, jika berlanjut hingga Desember, juga tidak ada apa-apa. Jika berlanjut, apakah itu semua bisa mengobati kegetiran yang kita alami tiga bulan terakhir? Belum tentu juga.
Dalam negeri pun demikian. Wacana kembalinya IBL pada 4 September nanti juga belum bisa dibilang final. IBL harus menunggu restu Perbasi untuk hal itu. Menariknya, di waktu yang hampir bersamaan, Perbasi merilis surat untuk melarang kegiatan basket dalam jumlah banyak, untuk sementara ini.
Nantinya pun, jika IBL sudah mendapatkan restu, apakah para pemain juga langsung sepakat bermain semua? Atau ada juga penolakan seperti Kyrie yang berdasarkan faktor-faktor lain di Indonesia? Hal ini tak bisa dikesampingkan mengingat kondisi di Indonesia sendiri semua serba tidak jelas.
Deretan persoalan di atas membuat saya, sebagai penikmat basket, juga kebingungan dan akhirnya merasa bahwa untuk saat ini, kehadiran pertandingan-pertandingan olarhaga tidak bisa membantu banyak di tengah pandemi. Untuk saat ini, dunia mungkin menyerah terhadap pertandingan olahraga. Untuk kali ini, olahraga tampaknya tak bisa menyelesaikan persoalan dunia.
Foto: NBA


























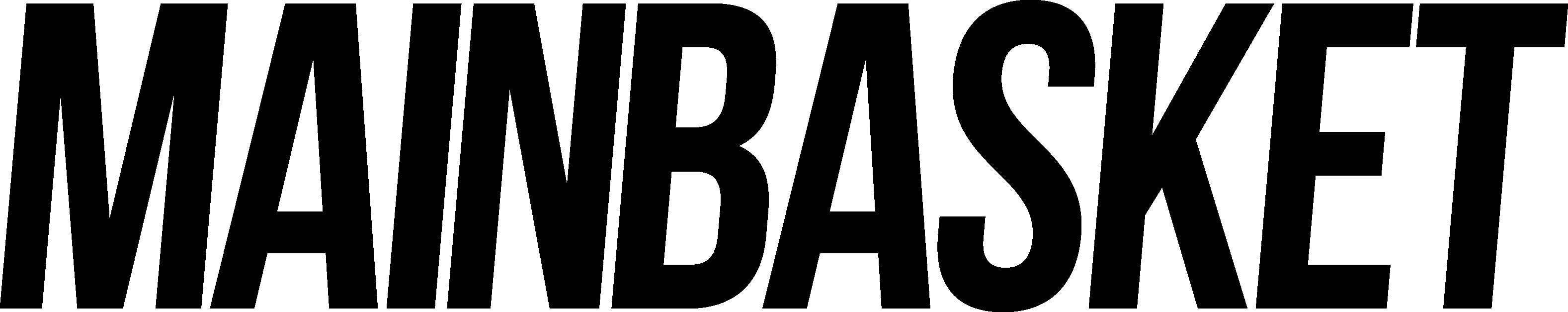




 0822 3356 3502
0822 3356 3502