Suatu hari, pada medio 2013, seorang pemain sayap bergabung dengan Manchester City, klub sepak bola Liga Inggris favorit saya. Namanya Jesus Navas, berkebangsaan Spanyol, diboyong dari Sevilla dengan harga mencapai £14,9 juta. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia pun meninggalkan rumah, melanjutkan kariernya dengan jauh dari keluarga.
“Ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk mengambil langkah ini,” kata Navas. “Saya sangat senang dengan kesempatan dan keputusan ini.”
Navas adalah pemain sayap yang cepat. Larinya seperti kilat. Pada 2016, The Telegraph sempat menempatkannya di peringkat 18 dalam daftar pemain tercepat di Liga Inggris bersama Eric Pieters. Kecepatannya saat itu mencapai 34,65 kilometer per jam.
Navas kelihatannya baik-baik saja dari luar. Ia sama seperti pemain lain. Namun, tidak sesungguhnya. Navas punya cerita menarik yang membuat saya terkejut.
Navas menderita kerinduan kronis akan rumahnya (homesickness). Dalam artian, ia tidak bisa jauh dari Sevilla, kampung halamannya. Navas bahkan pernah mengalami serangan cemas dan kejang-kejang. Ia terpaksa menolak tur pramusim bersama Sevilla ke Amerika Serikat, meski pada akhirnya tetap pergi, untuk sekaligus mengatasi masalahnya, dan ia berhasil melakukan itu sampai sekarang.

Saat membaca cerita Navas, saya pikir kerinduan akan rumah separah itu tidak pernah ada. Saya pikir pergi jauh dari rumah adalah hal biasa. Sudah sejak lama manusia melakukan perjalanan-perjalanan. Paul Salopek, seorang jurnalis, saja bisa menelusuri jejak migrasi manusia dari Afrika ke Amerika Selatan dengan berjalan kaki selama tujuh tahun dalam proyek “Out of Eden”.
Saya pikir begitu. Namun, semuanya berubah ketika saya pindah dari Bandung ke Surabaya. Sebagai seorang pengelana pemula, saya berangkat dengan ekspektasi yang tinggi, bahwa Kota Pahlawan akan mewujudkan mimpi-mimpi saya. Sayangnya, hidup bukan tentang senang-senang saja. Hidup juga punya kesulitan-kesulitannya sendiri.
Kehidupan saya di Surabaya waktu itu baru berjalan sekitar 1,5 tahun. Namun, rasanya seperti sudah lama sekali. Tanpa keluarga dan teman-teman, waktu memang seolah berjalan lambat setiap hari. Saya mulai rindu akan rumah, tempat di mana bisa berbagi cerita tentang berbagai hal; dari yang lucu sampai yang serius. Menikmati kesederhanaan bersama keluarga. Berkembang dengan penuh gelora bersama teman-teman. Hidup sulit sekali tanpa mereka, terutama karena saya tidak mendapat gantinya. Surabaya tidak menyediakan “keluarga” dan “teman” dalam kamusnya. Kadang-kadang saya cemas karena takut tidak bisa melanjutkan hidup dengan baik.
Saya tentu bukan satu-satunya yang merasa begitu. Dalam babad kehidupan beberapa orang, berkelana memang bukan hanya tentang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada hal-hal yang mesti ditinggalkan. Ada hal-hal yang mesti disambut. Berkelana adalah sesuatu yang lain.
Bagi pemain bola basket NBA, misalnya, berkelana adalah sebuah persoalan kompleks. Setiap mendekati tenggat waktu transfer pemain, para penggemar boleh sangat bergairah, menunggu klub kesayangannya merekrut pemain yang hebat. Namun, pemain bisa saja merasa khawatir pada saat yang sama. Seandainya mereka harus pindah ke klub lain, maka mereka bukan hanya harus berganti kostum, tetapi lebih daripada itu.
***
Tyler Johnson baru saja bangun tidur saat mengetahui beberapa panggilan telepon yang tidak terangkat di ponselnya. Panggilan itu datang dari agennya. Johnson belum sempat bicara dengannya, tetapi ia tahu agennya akan berbicara tentang kepindahannya.
Benar saja, Miami Heat—klubnya saat itu—menukarnya ke Phoenix Suns. Johnson terpaksa pindah ke Arizona, meninggalkan keluarganya di Florida. “Anak-anak saya tetap tinggal di Miami,” katanya, sementara ia sendiri harus bergabung dengan klub baru di belahan lain Amerika Serikat.
Pindah klub bukan hanya tentang beradaptasi dengan sistem. Johnson mesti beradaptasi juga dengan kehidupan dan situasi baru di sekitarnya. Ia tahu itu tidak mudah, tetapi tetap melakukannya.
“Seperti orang-orang yang hidup jauh dari anak-anak mereka, ini sama sulit,” kata Johnson.
Johnson sendiri tentu memahami NBA sebagai entitas bisnis. Pada satu sisi, ia bisa menjadi barang dagangan. Namun, bukan berarti tidak bisa melepas emosinya. Sebab, selain sebagai pemain, Johnson juga seorang kepala keluarga. Ia punya anak-anak yang mesti dibesarkan.
“Kita merasakan hal yang sama. Pada akhirnya, kita ini masih manusia,” tambah Johnson.

Untungnya, Suns bersedia untuk membantunya beradaptasi. Mereka berada dekat dengannya agar Johnson bisa melakukan transisi selancar mungkin. Manajemen klub memastikan ia nyaman di rumah barunya.
Pada awalnya, semua memang berjalan lancar. Johnson mulai terbiasa dengan Phoenix. Anak-anaknya juga beberapa kali mengunjunginya di sana, dengan mengenakan jersei bernomor punggung 16 miliknya. Namun, NBA tetaplah NBA. Mereka adalah entitas bisnis.
Suatu hari, Johnson mengalami cedera lutut kanan. Ia mesti meninggalkan lapangan selama sisa musim pada 4 April 2019. Naik ke meja operasi untuk melakukan arthroscopy. Sejak saat itu, kesulitan demi kesulitan menghampiri.
Johnson sebenarnya sempat tampil dalam 31 pertandingan pada 2019-2020. Namun, tidak lagi menjadi pilihan utama Suns. Mereka sudah punya garda yang lebih mapan dalam diri Ricky Rubio. Suns pun melepas Johnson pada 9 Februari 2020. Ia kini seorang pemain bebas—tidak punya klub untuk bernaung.
Itu artinya, Johnson lagi-lagi harus pindah. Untuk sementara ini, ia bisa pulang ke Florida, bertemu keluarganya yang hidup terpisah selama beberapa waktu. Namun, seandainya suatu hari Johnson mendapatkan klub baru, dan klub baru itu tidak berada di Florida, maka ia mesti pindah lagi. Pindah berarti berurusan dengan adaptasi sistem plus hal lain yang lebih besar dari itu. Bahkan, kalau kontraknya tidak berjangka panjang, Johnson mungkin harus hidup terpisah dengan keluarganya seperti dulu.
***
NBA memutuskan untuk menunda musim kompetisi 2019-2020. Mereka terpaksa melakukan itu karena pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona (SARS-CoV-2). NBA sampai menutup fasilitas-fasilitas klub dan melarang pemain untuk berpergian keluar negeri. Mereka mengimbau agar pemain tetap berada di rumah. Padahal tidak semua pemain berasal dari Amerika Serikat.
Tomas Satoransky, misalnya, kesal karena dirinya tidak bisa pulang ke Republik Ceko pada saat krisis seperti ini. Ia terjebak di Amerika Serikat bersama istri dan anaknya tanpa bisa mengunjungi keluarga mereka di kampung halaman. Satoransky masih menunggu keputusan NBA untuk menyetop kompetisi. Namun, liga tersohor sedunia itu tampaknya bergeming. Mereka dan para pemilik klub tetap ingin melanjutkan kompetisi sehingga pemain seperti garda Chicago Bulls itu tidak bisa ke mana-mana.
“Rasanya tidak menyenangkan sama sekali tinggal di sini dan menonton bagaimana para pemilik klub mencoba merampungkan musim agar tidak kehilangan banyak uang,” kata Satoransky. “Rasanya tidak terlalu menyenangkan juga karena kami—saya dengan istri dan anak perempuan saya—ingin pulang ke Republik Ceko.”

Satoransky sebenarnya tidak sendirian. Pada saat seperti ini, semua pemain mengalami kesulitan masing-masing. Bogdan Bogdanovic, forwarda Sacramento Kings asal Serbia, mengaku sulit melatih diri. Fasilitas-fasilitas klub ditutup. Ia mesti berlatih sendiri di rumah.
Bogdanovic takut kalau-kalau latihan di rumah tidak maksimal. Namun, apa daya, pemain sepertinya harus tetap menjaga tubuh dengan berbagai cara. Sebab, kompetisi tidak akan berhenti. Ia mesti bertanding lagi suatu hari nanti. Sementara keluarganya di Serbia berharap-harap cemas tentang nasibnya.
Bagaimana pun, virus corona telah mengacaukan segalanya. NBA saat ini mengalami hiatus dan tidak jelas juntrungannya. Masa depan liga tidak tertebak. Marco Belinelli, garda San Antonio Spurs berkebangsaan Italia, bahkan tidak mau berkomentar banyak. Saat ini, semuanya tampak abu-abu. Satu hal yang pasti: Mereka mesti tetap di rumah saja.
Meski begitu, Amerika Serikat bukanlah rumah yang benar-benar rumah bagi mereka. Satoransky saja ingin pulang ke Republik Ceko agar bisa bertemu keluarga. Persoalan rumah memang bukan persoalan tempat tinggal. Elvis Presley, lewat lagunya berjudul Home Is Where The Heart Is, mengatakan bahwa rumah adalah di mana hati kita berada.
***
Surabaya memang masih menjadi tempat yang membuat saya kesulitan. Seperti Johnson, saya mesti hidup jauh dari keluarga, juga teman-teman. Namun, pulang sekarang bukan sebuah jalan keluar. Saya telanjur menggantungkan mimpi-mimpi saya di sini. Ada yang menunggu untuk diwujudkan.
Satoransky mungkin memahami perasaan saya saat ini. Kami sama-sama ingin pulang, tetapi ada satu dan lain hal yang membuat kami tertambat, dan kami tidak bisa melepas tambatan itu begitu saja. Sebab, ada sesuatu yang mesti diselesaikan. Entah itu mengikat karena kontrak dari diri sendiri atau dengan orang lain.
Pada titik seperti ini, yang saya butuhkan adalah keseimbangan hidup antara menjaga kewarasan dengan berusaha mewujudkan mimpi-mimpi tadi. Rubio, garda yang kini menggantikan peran Johnson di Suns, mungkin tahu caranya. Ia punya sebuah hobi unik.
Pada musim panas lalu, setelah memenangi gelar juara Piala Dunia 2019 bersama Spanyol, Rubio menandatangani kontrak dengan Suns, kemudian mendekorasi tempat tinggalnya di Phoenix. Ia pergi ke IKEA untuk membeli furnitur dan memasangnya di suatu sudut di rumahnya. Meski nilai kontraknya mencapai AS$51 juta, dan itu tentu bisa dipakai untuk menyewa tukang, Rubio selalu memastikan segalanya sesuai keinginan dengan tangannya sendiri.
Rubio pindah dari Spanyol ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Minnesota Timberwolves pada 2011, pindah ke Utah Jazz pada 2017, pindah lagi ke Suns pada 2019, dan selalu membeli sekaligus memasang dekorasi tempat tinggalnya sendiri. Bayangkan, berapa kali Rubio harus melakukan itu?

Hidup di negeri orang bukan perkara mudah. Rubio paham. Maka dari itu, ia perlu kegiatan-kegiatan yang membuatnya seimbang. Membeli serta memasang dekorasinya sendiri adalah salah satu bentuknya.
Selain soal pertukangan, Rubio mulai mendalami yoga dan meditasi selama beberapa tahun ini. Ia juga bermain catur meski sulit mencari lawan. Pada zaman ini, orang-orang lebih senang berselancar di internet. Namun, Rubio tetap bermain catur. Menurutnya, catur adalah metafora kehidupan.
Bermain bola basket di level yang tinggi membuat Rubio mendapatkan tekanan yang tinggi pula. Oleh karena itu, ia perlu sesuatu yang membuatnya tidak stres. Bukan malah menambah beban sehingga menyebabkan kecemasan.
“NBA adalah kehidupan yang sulit,” ujar Rubio. “Kami bermain bola basket, dan kami tertawa ketika melakukannya, tetapi ada sesuatu yang muncul yang mungkin Anda suka atau tidak, dan Anda harus mengatasinya.”
Untuk mencapai keseimbangan hidup, Rubio bahkan sampai mengurangi penggunaan ponsel. “Semakin sedikit saya menggunakan ponsel, semakin bahagia saya,” katanya. Orang-orang seperti Rubio adalah contoh dari para pengelana yang mencapai titik seimbang. Ia sadar bahwa tempat tinggalnya sekarang penuh tekanan. Namun, tahu caranya mengurangi tekanan itu dengan gaya hidup yang holistis. Ia melatih tubuh dan pikirannya agar mencapai rasa nyaman dan percaya diri yang baik.
“Ia sangat mendalami ini. Ia menggali apa yang penting baginya dengan sungguh-sungguh, ke dalam nilai-nilainya, ke dalam prinsip-prinsip utamanya,” kata Sergio Scariolo, kepala pelatih tim nasional Spanyol, yang kagum kepada sosok Rubio saat ini. “Apa yang ia alami sebagai seseorang, melalui rasa sakit, melalui kapasitas untuk pulih dari kehilangan yang berat, ia mendapatkan keseimbangan pribadi dalam kehidupannya di luar lapangan sekarang.”
Seperti kata Scariolo, Rubio memang sempat mengalami kehilangan yang berat. Pada 2016, ibunya meninggal karena kanker paru-paru. Kematian sang ibunda membuat Rubio terpukul. Namun, ia berhasil mengatasinya. Rubio tahu betul bahwa kehidupannya tidak akan berhenti di sana.
Foto: NBA

























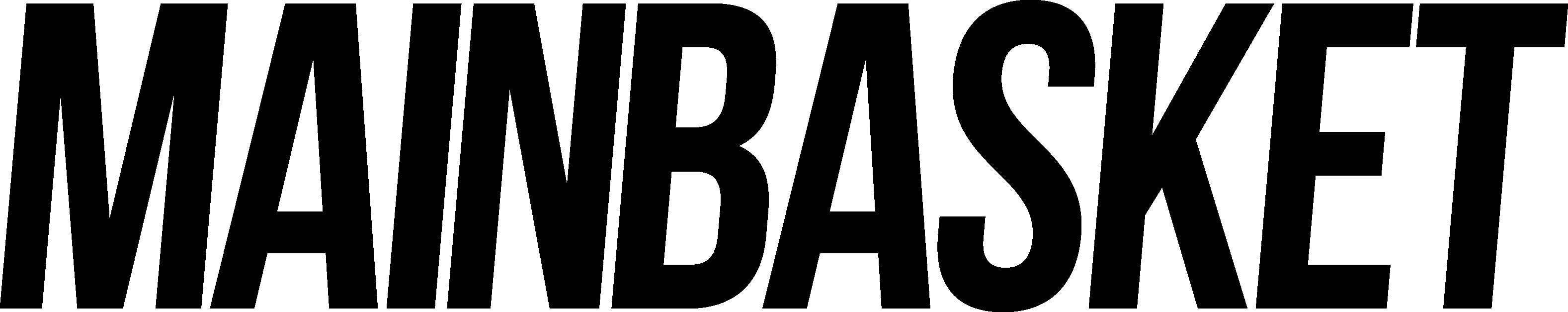




 0822 3356 3502
0822 3356 3502