Chicago Bulls merupakan tim dengan sejarah yang dikenang oleh semua penggemar olahraga bola basket angkatan 1990-an. Mereka adalah tim legendaris dengan dua kali three peat (gelar juara tiga kali beruntun). Mereka mempunyai pemain terbaik dalam sejarah olahraga bola basket, yaitu Michael Jodran. Namun setelah generasi tersebut, prestasi Bulls terjun bebas.
Harapan kembali muncul ketika Bulls mendapatkan pemain muda fenomenal, Derrick Rose. Pada musim kompetisi 2010-2011, Rose mendapatkan gelar pemain terbaik (MVP). Dia menjadi pemain Bulls pertama yang meraih gelar tersebut sejak berakhirnya dinasti Jordan.
Pada musim tersebut, Bulls juga berhasil mencapai final NBA Wilayah Timur. Namun, harus mengakui kekalahan dari Miami Heat yang diperkuat LeBron James, Dwyane Wade, dan Chris Bosh.
Performa yang ditunjukkan pada NBA 2010-2011 membuat harapan terhadap Rose dan Bulls semakin tinggi. Hanya saja, harapan itu bagai kabut asap yang cepat hilang. Pada NBA 2011-2012, Rose terkena cedera ACL. Dia harus menepi selama dua musim.
Sejak itu, harapan perlahan sirna. Bulls juga tidak berani memeprtahankan Rose lagi. Sang MVP bersama Justin Holiday dikirim ke New York Knicks dengan sistem pertukaran pemain.
Ketika Rose pergi, Bulls kembali membangun ulang timnya. Pada NBA 2017-2018, mereka menukar aset terpenting, Jimmy Butler, untuk mendapatkan Zach LaVine, Kriss Dunn, dan Lauri Markkanen. Bulls ingin membangun tim dengan berpusat pada LaVine. Namun, lagi-lagi faktor cedera menghambat performa Bulls. LaVine hanya dapat menyelesaikan 24 laga.
LaVine kembali pada NBA 2018-2019. Bahkan, musim kompetisi tersebut, ia menampilkan performa terbaik selama lima tahun bermain di NBA. Dia memiliki rata-rata 23,7 pts dengan efektivitas tembakan 52 persen.
LaVine juga memiliki efisiensi serangan 1,05 angka pada setiap penguasaan dengan menggunakan 29,8 persen USG. Efisiensi serangan tersebut sudah berada diatas rata-rata liga.
Walau demikian, penampilan tersebut belum cukup untuk membawa LaVine tampil di level All-Star. Dalam 10 tahun terakhir, hanya LaVine, Danny Granger (2009-2010) dan Bradley Beal (2016-2017) yang tidak dapat tampil di All-star ketika mempunyai rata-rata 23 atau lebih produktivitas angka. LaVine hanya satu kali memiliki efisiensi serangan yang tidak mendukung kesuksesan tim, yaitu pada musim perdananya di NBA. Hanya saja, selisih bersih yang dihasilkan selau negatif. Buruknya efisiensi bertahan menjadi faktor belum berhasilnya ia mencapai level All-Star.
Pada 2018-2019, LaVine memiliki kemasukkan 1,1 angka pada setiap penguasaan lawan. Dengan rincian, sebagai berikut: 54,5 persen menjaga lawan di area tiga angka dan 45,5 persen menjaga lawan di area dua angka. Area tiga angka, yang memiliki distribusi tertinggi, menjadi kontributor buruknya LaVine dalam bertahan. Dia kemasukkan rata-rata 2,1 tembakan tiga angka dari rata-rata 5,4 upaya tembakan tiga angka dengan presentase keberhasilan 39 persen. Presentase keberhasilan tersebut di atas rata-rata liga. Sedangkan pada area dua angka, LaVine berhasil menekan presentase keberhasilan lawan di bawah rata-rata liga. Dia kemasukkan rata-rata 2,3 angka tembakan dua angka dari rata-rata 4,5 upaya tembakan dua angka (51,3 persen).
Peningkatan performa sudah diperlihatkan LaVine pada saat masa NBA Pramusim 2019. LaVine berhasil memperbaiki kelemahan dalam hal efisiensi bertahan dan mempertajam keunggulan efisiensi serangan. Konsistensi performa seperti pada saat NBA Pramusim 2019 akan membuat peluang LaVine untuk menembus level All-Star semakin terbuka. Terpilihnya LaVine dalam roster All-Star akan membuat tuan rumah, Chicago, memiliki satu wakil di All-Star setelah berakhirnya era Rose.
Semoga asap harapan tersebut tidak kembali hilang.
Foto: NBA













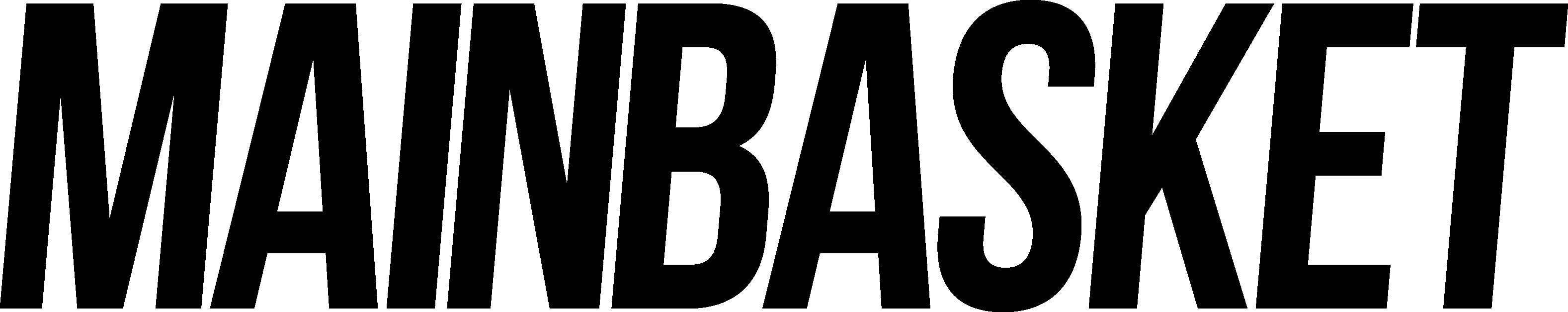




 0822 3356 3502
0822 3356 3502