Saya berdiri tegak di balik meja media ketika lagu Indonesia Raya berkumandang. Di samping saya, beberapa kawan melakukan hal yang sama. Para pemain dan jajaran pelatih yang akan melakoni pertandingan final Honda DBL East Java Series 2019 juga begitu. Sementara seisi gelanggang DBL Arena Surabaya terbius dalam khidmat menyanyikan lagu kebangsaan.
Ketika Indonesia Raya berkumandang, saya tidak bisa menyapu pandangan. Sesuai Undang-Undang, saya hanya bisa berdiri dengan sikap sempurna. Memandang lurus ke barisan pendukung SMAN 2 Surabaya yang mengenakan kaus kuning di seberang sana.
Tidak lama setelah semua orang menyanyikan lirik “Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku…”, tiba-tiba pikiran saya melompat ke tempat lain. Dada saya sesak. Dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk: sedih, marah, dan kecewa.
“Asu! Nyanyi Indonesia Raya begini pengen nangis,” batin saya kemudian. Saya bahkan mengirim pesan yang sama kepada kekasih saya via aplikasi obrolan.
Saya sedih, marah, dan kecewa karena teringat demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah belakangan ini. Utamanya di Jakarta. Para mahasiswa, juga masyarakat dari berbagai kalangan, turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus pemerintah. Sebab, wakil rakyat dan pemerintah itu serampangan saja sehingga butuh diingatkan berkali-kali oleh rakyatnya sendiri.
Saya tahu dan sangat sadar bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di Jakarta, mahasiswa yang berdemonstrasi dipukuli polisi. Aktivis juga ditangkapi. Belum lagi buzzer-buzzer kurang ajar di media sosial dengan segala hoaks yang menyebalkan.
Kemudian, di Kendari, seorang mahasiswa meninggal dunia akibat tertembak peluru tajam. Ayahnya, seorang nelayan, mendapati jasad anaknya sepulang melaut—sudah tidak bernyawa.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kita untuk tidak meragukan komitmennya terhadap demokrasi. Setelah semua kekacauan yang terjadi? Entah dagelan apa yang sedang dipertontonkannya. Saya tidak mengerti.
Mengingat itu membuat bibir saya bergetar ketika menyanyikan Indonesia Raya. Tangis saya hampir tumpah, tetapi saya menahannya. Saya ingin tegar. Setidaknya terlihat tegar di hadapan kawan-kawan. Saya tidak ingin mengundang pertanyaan siapa pun. Ujung-ujungnya, mata saya berkaca-kaca.
Setelah Indonesia Raya berkumandang, saya mengusap mata, lutut saya juga lemas. Saya langsung duduk di balik meja. Tanpa kursi. Sebab, di sana sudah penuh sesak. Kursi-kursi sudah diambil alih. Sementara di tempat lain tidak ada banyak spot untuk duduk menghadap lapangan.
Ketika menghadap lapangan itu, saya menatap satu per satu wajah mereka yang akan bertanding. Tidak terkecuali para pelatih.
Saya kemudian memindahkan pandangan ke belakang. Di atas tribun sana, siswa-siswi SMA St. Louis 1 Surabaya mengenakan kaus merah. Mereka mulai menabuh drum. Beberapa menyanyikan lagu-lagu.
Dari wajah-wajah itu, tiba-tiba muncul pikiran lain. Cenderung muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya. Satu pertanyaan terasa penting.
“Seandainya mereka besar, mereka akan jadi apa?”
Saya memperhatikan siswa-siswi itu dari kiri ke kanan, lalu sebaliknya. Berulang-ulang. Untuk mendapatkan jawaban dari satu pertanyaan tadi.
Saya—tentu saja—tidak mendapatkan jawabannya. Mereka belum akan menjadi apa-apa. Mereka masih SMA. Seorang pelajar. Namun, sungguh, jadi apa pun mereka nanti, semoga bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Jean Marais—seorang tokoh dalam buku Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer—pernah berkata, seorang pelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan.
Saya pun kembali memandang lapangan. Wasit melempar bola tepis mula. Pertandingan dimulai. Sejak itu Indonesia Raya tidak pernah sama lagi.
Foto: DBL Indonesia
























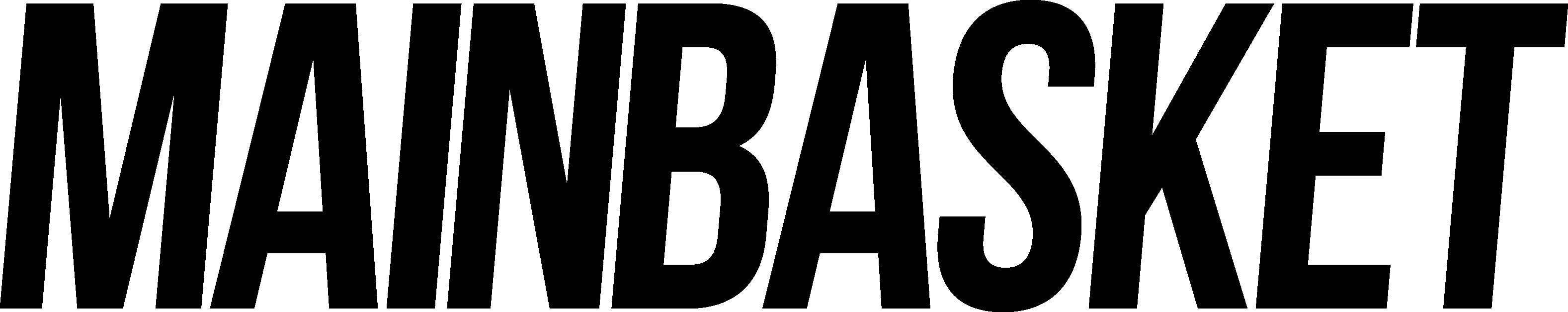




 0822 3356 3502
0822 3356 3502