Sepi penonton adalah ongkos termahal gelaran kompetisi olahraga.
Saya tahu. Saya tahu, kalimat judul di atas barangkali agak sulit dipahami. Padahal, makna sebenarnya tidaklah serumit itu untuk dicerna. Saya menulis ini karena sempat termenung dengan beberapa komentar di unggahan instagram @mainbasket mengenai tak adanya juara nasional dalam kompetisi Honda DBL.
Menemukan satu sekolah dengan kekuatan terbaik dari seluruh peserta Honda DBL di 30 kota di Indonesia memang menarik. Apalagi jika sebelumnya sekolah-sekolah yang berhasil juara itu dikumpulkan terlebih dulu di satu kota untuk kemudian diadu. Dikompetisikan.
Membayangkannya saja, saya sudah langsung bergairah. Saya mengkhayalkan bagaimana deg-degannya sekolah-sekolah juara dari kota-kota di pulau Jawa ketika mereka akan saling bertemu. Ada pula rasa was-was tim-tim dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, Nusa Tenggara dan Bali ketika mereka akan bertarung melawan tim-tim dari Jawa, yang konon katanya level basketnya ada satu bahkan beberapa level di atas mereka.
Rasanya akan keren banget ketika ternyata juaranya adalah sekolah dari Kalimantan. Lalu tahun berikutnya sekolah dari Merauke. Berikutnya lagi Jakarta dan Surabaya bertemu di final. Tiba-tiba di luar dugaan sekolah dari Kupang menang tipis di final dari sekolah kuat di Bandung. Bayangan-bayangan tersebut muncul di benak saya ketika membayangkan andai saja DBL punya kompetisi semacam itu. Kompetisi yang mengadu juara lokal untuk menemukan jawara nasional.
“Siapa yang mau bayarin?”
Pertanyaan tersebut membuyarkan khayalan saya. “Pufff..”, seperti suara balon gelembung sabun pecah (kalau ada suaranya) yang melayang di udara ketika terkena sentuhan lembut apapun yang berbenturan dengannya.
Siapa yang mau mengeluarkan uang untuk mendanai transportasi dan akomodasi setiap tim sekolah yang berangkat ke satu kota penyelenggaraan kejuaraan nasional tersebut?
Bisa jadi ada sekolah yang mampu bayar sendiri. Namun rasanya akan lebih banyak yang harus pusing tujuh keliling cari pendanaan.
Pertanyaan kedua, yang tak kalah penting dan terkait dengan judul tulisan ini adalah, “Siapa yang mau nonton?”
Seriusan, siapa yang mau nonton gim-gim penyisihan antara dua sekolah luar kota yang dipisahkan tiga sampai empat lautan?
“Kalau pertandingannya menarik, pasti banyak yang nonton!”
Pertandingannya menarik atau tidak, baru akan ketahuan setelah gimnya selesai.
“Siapa yang mau nonton?” ini adalah pertanyaan penting. Super penting. Sangat penting sampai-sampai akan berjalannya kompetisi sejenis ini atau kelangsungan hidup sebuah kompetisi akan sangat bergantung pada pertanyaan ini.
Kerap kali membicarakan kompetisi basket di level apapun dengan siapapun, saya seperti mendengarkan khayalan saya dalam bentuk ucapan teman-teman saya. Mereka pun membayangkan memiliki kompetisi serupa. Sebuah kompetisi ketat, bergengsi, penuh kejutan, dan ramai penontonnya. Sejujurnya, saya kadang lebih ingin membicarakan hal yang sedikit lebih jauh tadi.
“Siapa yang mau bayarin?”
“Siapa yang mau nonton?”
Butuh uang yang sangat besar untuk menyelenggarakan ajang-ajang olahraga ternama di dunia, sebut saja NBA, sepak bola Liga Inggris, Liga Spanyol, Piala Dunia, olimpiade, dan lain-lain. Mereka bergulir mulus karena berhasil menjawab dua pertanyaan di atas.
“Yang bayarain adalah sponsor dan (tiket) penonton.”
Pendana kedua, alias penonton, bisa jadi menyumbangkan nominal lebih sedikit daripada sponsor. Namun signifikansinya sangat besar. Semakin banyak potensi penonton atau yang sudah menonton (berdasar rekam jejak sebelumnya), maka semakin besar pula peluang sponsor dengan duit banyak yang akan datang mendukung. Tanpa penonton (penonton sedikit), tak ada sponsor yang mau mendekat. Tanpa penonton, sponsor yang sudah ada bisa kecewa, dan sangat mungkin tak akan kembali di tahun atau gelaran berikutnya.
Banyak penyelenggara kegiatan olahraga terlalu sibuk mencari sponsor, tetapi lupa mencari penonton. Ironisnya, ada yang sudah dapat sponsor, malah tak ingat dengan penontonnya. Bahaya.
“Jadi, bagi sponsor, tak penting siapa yang tanding. Tetapi siapa, atau tepatnya, berapa banyak yang nonton?”
100! Tepat! Betul!
Dengan berbagai cara, Honda DBL berhasil mengumpulkan penonton fanatik dari setiap sekolah yang berlaga di 30 kota. Ini bukan pekerjaan mudah. Ada yang menyangka bahwa fanatisisme sekolah membuat para siswa otomatis datang mendukung tim sekolahnya yang berlaga. Tidak juga. Kalau ya, seharusnya setiap kompetisi olahraga yang membawa nama sekolah akan selalu dipadati penonton.
Kalau mau mengadakan atau mencari juara DBL nasional, panitia, atau PT DBL Indonesia harus menemukan cara jitu agar penontonnya ramai. Tantangannya akan berbeda dengan mengumpulkan penonton di 30 kota. Mungkin DBL bisa. Mungkin masih ragu.
Kalau sekadar menyelenggarakan saja, mengumpulkan 30 tim sekolah di satu kota, lalu menemukan juara nasional, rasanya terlalu mudah, bahkan sangat mudah bagi DBL. Namun bila setelah kompetisi seperti itu akhirnya berhasil digelar dan penontonnya tak memenuhi ekspektasi, maka rasanya para pembaca yang sudah sampai di kalimat ini akan sadar, bahwa:
“Kompetisi dengan penonton yang sedikit itu terlalu mahal harganya.”(*)
Foto: McD












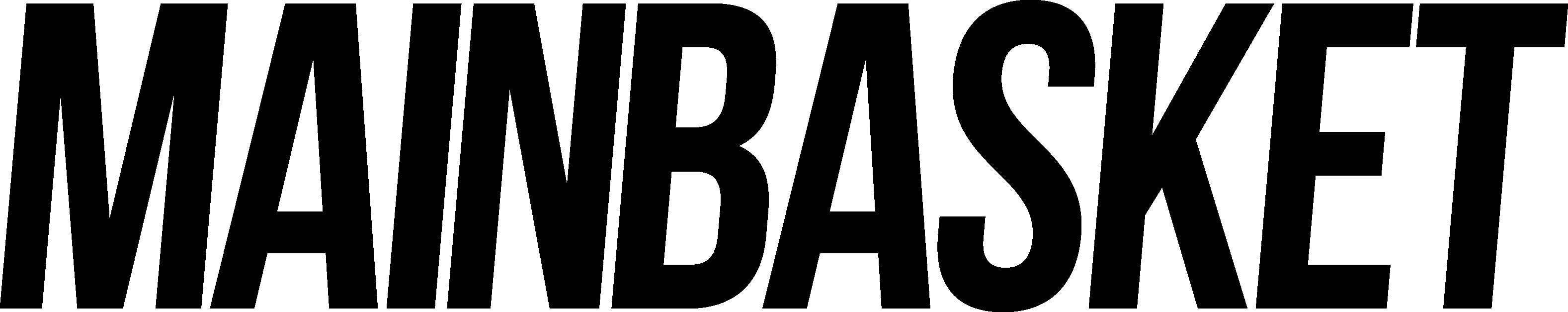




 0822 3356 3502
0822 3356 3502