Tulisan ini seharusnya sudah keluar beberapa hari lalu. Karena pada 4 Juli lalu, ada ulang tahun yang sangat penting. Tepatnya: Ulang tahun ke-15 DBL Indonesia.
Ya, waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa, sudah 15 tahun saya dan teman-teman jadi penyelenggara liga basket pelajar terbesar di Indonesia.
Secara resmi, DBL (nama orisinalnya DetEksi Basketball League) memulai hari resmi pertamanya pada 4 Juli 2004. Hari itu, kami menyelenggarakan technical meeting pertama di Surabaya. Dihadiri perwakilan 96 tim SMA dari berbagai kota di Jawa Timur.

Pada hari itu, regulasi orisinal dibahas. Mengedepankan konsep student athlete, di mana nilai rapor menjadi salah satu elemen penting pendaftaran. Karena sebelum itu, sangat umum bagi anak basket untuk tidak naik kelas. Bahkan, ada yang tidak naik kelas tiga tahun masih tetap main basket SMA!
Technical meeting itu begitu “meriah.” Maksudnya, ramai dan kadang emosional, ketika para pelatih dan perwakilan sekolah membahasnya. Sampai-sampai ada yang walkout, dan akhirnya peserta yang bertanding berkurang satu, jadi 95 tim.
Idealisme memang ditetapkan sejak awal. Liga ini tujuannya tidak langsung untuk mencari atlet. Melainkan untuk meningkatkan partisipasinya, sekaligus menjaga agar atlet hebat –siapa pun dia-- tetap harus melewati sekolah dengan baik.
Alhamdulillah, liga ini “meledak.” Rekor penonton terus dipecahkan di Jawa Timur. Stadion “isi ulang” penonton sudah jadi pemandangan sehari-hari.
Padahal, dari awal DBL sudah bikin repot diri sendiri. Bahwa penonton harus bayar. Awalnya dulu Rp 3.000 per tiket. Kompetisi lain waktu itu hampir semuanya gratis karena takut tidak ada penonton.
Alasannya sederhana, kalau mau bertahan jangka panjang, model kerjanya harus sustainable. Lebih baik sepi di awal tapi bertahan lama, daripada penonton banyak tapi tahun depannya hilang.
Pada 2007, peserta sudah tembus 220 peserta. Padahal masih di Jawa Timur. Sudah waktunya untuk ekspansi secara nasional. Tapi secara bertahap. Bersama PT Astra Honda Motor, DBL pun go national!
Sepuluh provinsi pada 2008, 15 provinsi pada 2009, dan sekarang sudah 30 kota di 22 provinsi. Peserta sekarang sudah tembus 40 ribu orang, dengan penonton mendekati angka 1,5 juta per tahun.
DBL juga sudah go international. Menjadi liga pertama di Indonesia yang menjalin kerja sama resmi dengan NBA. Lalu mengirim peserta/tim secara rutin ke Amerika, Australia, Malaysia, dan lain-lain.
PT DBL Indonesia, yang dibentuk pada 4 Juli 2008, sekarang sudah memiliki karyawan hampir 300 orang. Kalau digabung dengan kru part time di 30 kota itu, setiap tahunnya kompetisi pelajar kami melibatkan tim sekitar 1.000 orang!
Yap, sebuah liga SMA (dan SMP) yang mempekerjakan 300 karyawan full time dan total 1.000 pasukan!
***
Waktu memang berlalu begitu cepat. Perjalanan DBL merupakan perjalanan pribadi saya. Usia saya masih 27 saat DBL dimulai, dan sekarang… Sudah 15 tahun kemudian.
Bahkan anak pertama saya, Ayrton, lahir di tengah-tengah kesibukan mengembangkan DBL. Ayrton lahir 24 Januari 2008. Tepat di tengah-tengah puncak kesibukan/keseruan DBL di Mataram, Lombok.
Saya ingat betul. Tanggal 23 saya masih di Lombok, saat kompetisi sudah mengerucut di perempat final. Saya cepat-cepat pulang, karena istri sudah hendak melahirkan. Dan besok paginya anak pertama saya lahir. Tidak lama, saya segera balik lagi ke Lombok, demi persiapan laga final tanggal 26.
Saya tidak mungkin meninggalkan puncak laga Lombok itu. Karena itulah kompetisi pertama DBL di luar kandang sendiri, di luar Jawa Timur. Itu adalah langkah pertama kami go national.

Gara-gara DBL, saya jadi melihat Indonesia secara komplet. Terbang ke sana ke mari, dari Aceh sampai Papua. Pernah terbang 75 kali dalam 90 hari, menyambi DBL dengan pekerjaan utama waktu itu.
Dan saya memandang Indonesia dari sudut pandang yang unik: Dari sudut pandang anak mudanya.
Tidak peduli apakah Anda anak muda di Aceh, Jakarta, Jogjakarta, Manado, Bali, atau Papua, semua pada dasarnya sama. Semua punya potensi yang begitu luar biasa, semangat dan antusiasme yang luar biasa, tapi terbatasi oleh terbatasnya platform atau panggung untuk menunjukkan kemampuan.
Saya lega, DBL bisa memberi panggung yang konsisten. Panggung yang membuat anak di Aceh merasakan atmosfer yang setara dengan yang di Jakarta atau Surabaya.
Lima belas tahun sudah berlalu. Saking lamanya, perjalanan DBL saya rasakan bahkan saat traveling ke luar negeri. Kalau disapa mantan peserta DBL di Singapura dan Malaysia sudah biasa. Tapi disapa di Australia, atau bahkan di Amerika, rasanya surreal (takjub sekaligus aneh).
Saya pernah disapa mantan anak DBL di sebuah tram di Melbourne. Waktu itu rasanya bangga, karena dia kenal saya tapi tidak kenal ayah saya yang seharusnya jauh lebih kondang. Wkwkwkwk…
Terakhir, di penghujung 2018 lalu saat ke Sydney. Saat di kawasan Harbour Bridge, ada yang menyapa saya. Saya tidak familiar, tapi dia langsung memperkenalkan diri sebagai peserta DBL… Dari Pontianak! Sekarang dia sudah bekerja dan tinggal di Sydney.
Surreal rasanya, ketika bertemu mantan peserta DBL di bandara-bandara, di pertemuan-pertemuan bisnis, dan lain sebagainya.
Dan jangan bilang soal atlet nasional. Para bintang basket nasional yang berlaga di Asian Games dan lain-lain banyak mantan peserta DBL.
Ada yang saya sudah tahu betul kecilnya bagaimana, sekarang dia sudah merasakan menjadi juara di liga basket internasional. Ada yang waktu SMA agak nangisan, sekarang sudah jadi pemain inti tim nasional.
Yang aneh lain? Pada 2010, Pak Jokowi membuka kompetisi DBL di Sritex Arena Solo. Waktu itu dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Tahun 2018, Pak Jokowi meresmikan pembukaan DBL secara nasional dengan bermain basket bersama para pemain SMA di Istana Bogor. Sebagai seorang presiden!
.jpg)
Jokowi sebagai wali kota saat pembukaan DBL Jawa Tengah di Solo 2010. Presiden Jokowi saat pembukaan DBL 2018 di Istana Bogor
***
Lewat DBL, saya juga bisa mengekspresikan berbagai breakthrough untuk terus mengembangkan industri olahraga. Sekali lagi, “agama” DBL adalah terus meningkatkan partisipasi.
Ada tulisan di depan ruang kerja saya, yang harus terus dicamkan oleh seluruh personel DBL Indonesia. Bunyinya: “Prestasi adalah cost, partisipasi adalah income. Kalau kita terus mengembangkan partisipasi, maka partisipasi akan membiayai prestasi.”
Kalau ingin mengembangkan sebuah olahraga (atau ajang partisipatif lain), yang paling utama adalah terus mengembangkan jumlah partisipasinya.
Yang didefinisikan sebagai partisipasi bukan hanya peserta/pemain. Penonton juga partisipan. Kalau partisipan peserta dan penonton terus bertambah, maka pertambahan partisipan sponsor ikut mengiringi.
Jangan berharap bisa besar kalau tidak bisa membesarkan “kue” partisipasi. Dan saya melihat ini sangat bermasalah di Indonesia. Ada begitu banyak cabang olahraga yang tidak pernah besar, tidak bisa besar, karena pengurusnya sama sekali tidak mengutamakan program partisipasi. Terus meributkan sebuah “kue kecil,” tidak sadar kalau tugas mereka seharusnya “membesarkan kue.”
Cilakanya lagi, banyak olahraga lebih mengutamakan percepatan instan. Tujuannya mungkin baik, supaya segera meraih prestasi. Tapi, kalau melakukan ini sambil mengabaikan partisipasi/grassroot, jangka panjangnya akan lebih hancur.
Untuk mengembangkan partisipasi, pakai saja prinsip bisnis. Cukup melakukan SWOT analisis sederhana. Mengidentifikasi, apa yang menjadi faktor penghalang pertumbuhan partisipasi olahraga yang Anda tekuni.
Di DBL, kami terus membahas ini untuk basket. Apa penghadang utama sebuah kompetisi basket bisa berkembang? Setelah kami pikir, salah satu kendalanya termasuk bola! Harga bola basket mahal, dan tidak ada merek asing yang mau mendukung kebutuhan sebesar DBL, yang jumlahnya ribuan pertandingan per tahun.
Solusinya, kami beruntung bertemu dengan Proteam. Merek bola nasional yang sebenarnya sudah kondang membuat bola-bola kebutuhan dunia. Sekarang, bola DBL adalah dengan bangga dibuat di Indonesia!
Kemudian, supaya peserta terus bertambah, kami bertanya lagi: Apa penghadang seorang anak untuk bisa bermain basket? Ternyata, barrier yang paling utama adalah sepatu.
Tidak banyak orang tua bisa membelikan anaknya sepatu basket seharga di atas Rp 1 juta. Apalagi Rp 2 juta. Apalagi kalau harus tetap membelikan sepatu lain untuk sekolah dan lain-lain.
Untuk menghancurkan dinding penghalang ini, kami pun agresif mengembangkan sepatu basket made in Indonesia yang harganya terjangkau.
Bersama Ardiles, DBL merilis sepatu AZA dan AD1 dan Pride, yang harganya di bawah Rp 500 ribu. Tujuannya bukan untuk keren-kerenan, apalagi jadi pesaing Stephen Curry atau Michael Jordan. Tujuannya murni supaya orang tua tidak marah-marah ketika harus membelikan sepatu basket!

Lucu, ada seorang sahabat di Jakarta yang mengeluh ke saya, kalau variasi warna sepatu AZA kurang banyak. Kebetulan dia penggemar sepatu basket dan koleksi sepatu-sepatu limited edition. Jawaban saya simple: “Ini sepatu bukan dirancang untuk kamu. Ini sepatu dirancang untuk anak-anak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, yang kesulitan membeli sepatu basket berkualitas.”
Saya bangga, sepatu ini direspon dengan sangat baik. Ini adalah sepatu basket terlaris di Indonesia. Bangga rasanya, ketika mampir di Magelang dan mampir ke toko sepatu kecil di pinggir jalan, ternyata ada sepatu AZA. Ketika mengunjungi kota mertua di Kediri dan mampir ke toko sepatu tradisional di pinggir jalan, ada sepatu AZA! Dan laku!
Jangan lupa juga untuk melakukan SWOT secara berkala. Karena segala dinding pembatas itu ikut berevolusi. Sepuluh tahun lalu, DBL dan para sponsor menghabiskan begitu banyak sumber daya dan energi untuk memaksakan program ini masuk TV. Sekarang? Tidak perlu TV! Bahkan, DBL “bermedia sendiri,” menghasilkan konten sendiri, menampilkannya sendiri lewat berbagai platform.
Kalau DBL bisa, yang lain pasti bisa.
Tentu saja, masih banyak kendala lain. Asal dihadapi satu per satu secara metodikal dan bertahap, semua akan ada solusinya. Tidak bisa instan. Tidak ada program percepatan yang bisa mengatasinya secara long term. Sekali lagi, tidak bisa INSTAN!
***
Lima belas tahun itu lama sekali. Dulu, pada 2008, saya bilang ke tim inti yang jumlahnya masih 15 orang. Bahwa DBL masih belum apa-apa. Masih jauh sekali dari potensinya.
Pada acara karyawan DBL Indonesia 4 Juli lalu, saya kembali bicara di depan tim, yang jumlahnya hampir 300 orang. Ucapan saya masih sama: DBL masih belum apa-apa, masih jauh dari potensinya.
Masih banyak yang bisa dilakukan untuk membuat DBL lebih besar lagi. Kita masih belum menjangkau semua kota di semua provinsi. Kita masih belum menuntaskan program-program yang terus “breaking barrier,” memecahkan dinding-dinding penghalang kemajuan anak muda, khususnya di dunia basket.
DBL Academy misalnya, di mana kami mencoba menerapkan akademi basket standar dunia sejak usia dini, masih mencoba berkembang. Sudah ada dua di Surabaya, dan dalam waktu dekat segera buka yang baru –dan spektakuler-- di Jogjakarta.

DBL Academy di Pakuwon Mal
Saya jadi ingat lagi ucapan ayah angkat saya waktu SMA dulu, John R. Mohn. Bahwa setiap manusia itu ada batas kemampuannya. Tapi, batas kemampuan itu bisa terus kita dorong ke atas, kalau kita tekun dan konsisten mendorongnya ke atas.
Tekun. Konsisten.
Lima belas tahun.
Kalau tidak tekun dan konsisten, mungkin tidak ada lima tahun pertama. Kalau tidak tekun dan konsisten, mungkin tidak ada lima tahun berikutnya. Apalagi 15 tahun.
Karena tekun dan konsisten, ternyata setelah 15 tahun masih belum kelihatan ujung potensinya. Karena kita terus menemukan pintu baru, menemukan jalan baru, menemukan cara baru, lalu diberi kesempatan-kesempatan baru.
Kalau kita selalu mencari jalan pintas atau instan, mungkin kita akan melewatkan jalan-jalan dan cara-cara baru itu. Jangankan mencoba cara atau jalan baru, melihatnya saja mungkin tidak!

Kepada seluruh kru dan partisipan DBL, terima kasih atas journey 15 tahun yang luar biasa ini. Masa depan masih jauh, masih panjang, masih belum kelihatan batasnya.
To infinity and beyond! (azrul ananda)
Foto judul: ivandarski













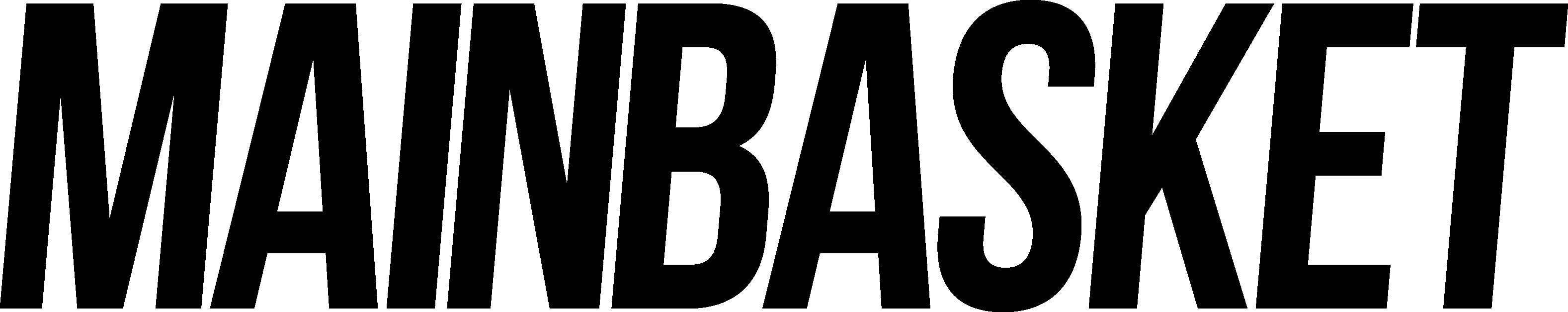




 0822 3356 3502
0822 3356 3502