Saya tidak akan menampik seandainya orang mengatakan bahwa hidup saya cenderung disetir oleh basket. Sebab, sejak mengenal olahraga permainan ciptaan James A. Naismith itu pada kelas lima SD, saya kadung jatuh cinta kepadanya. Apalagi basket selalu mampu memberikan keseruan yang tidak disangka-sangka.
Saat duduk di bangku SD, saya sebenarnya belum benar-benar mampu bermain basket. Saat itu saya hanya bisa melantun bola melewati selangkangan atau biasa disebut between the leg. Saya bahkan baru mengenal istilah between the leg ketika belajar basket di SMP. Ada jeda sekitar dua tahun sampai saya mengenal istilah itu.
Saya tinggal di Sukabumi, tepatnya di Cibadak, yang kultur basketnya hampir tidak terlihat. Internet juga belum semarak seperti sekarang. Sehingga informasi mengenai basket hampir sulit didapat, kecuali lewat DVD bajakan yang didapat di kios pinggir jalan. Itu pun sulitnya minta ampun. Meski pun sebenarnya—banyak juga pada zaman itu—orang-orang yang bermain basket. Salah satunya klub bernama Cibadak Streetball atau disingkat CSB.
Di klub itulah kemudian saya tumbuh. Pengetahuan saya tentang basket juga mulai berkembang. Saya mulai mengenal klub basket profesional bernama Aspac (kini Stapac) dan Garuda (kini Prawira). Dulu saya menyebutnya Aspac Bandung dan Garuda Jakarta. Padahal Aspac adalah klub asal Jakarta, sementara Garuda asal Bandung. Saya keliru. Maklum, informasi bisa simpang siur, bahkan di era teknologi yang semakin maju seperti sekarang.
Saya bergabung dengan CSB untuk pertama kali saat kelas sembilan SMP. Seperti anak-anak remaja pada umumnya—ketika sedang tekun kepada sesuatu—saya hampir melupakan segala hal di luar basket. Bahkan urusan cinta-cintaan pun tidak cukup saya pedulikan. Asal bisa bermain basket, pacaran itu hanyalah omong kosong dan buang-buang waktu.
Saya juga masih ingat saat pertama kali membeli bola basket. Waktu itu saya masih seorang anak SD. Belum berpenghasilan, uang jajan pun pas-pasan. Namun, karena kadung jatuh cinta dengan basket, saya menabung untuk membeli—setidaknya—satu bola untuk latihan.
Saya menyisihkan uang Rp1000 setiap hari untuk membeli bola basket yang harganya Rp20.000. Uang jajan saya sendiri waktu itu Rp2000. Jadi, setengah untuk jajan, setengah lagi untuk menabung.
Setelah terkumpul, saya langsung membeli bola di Indomaret Talang—sekitar 1,5 kilometer dari rumah—dengan berjalan kaki. Itu membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Berati pulang-pergi 30 menit. Silakan dihitung ulang. Siapa tahu saya salah.
Bola basket pertama saya itu terbuat dari karet. Saya tidak ingat mereknya, tetapi ingat warnanya. Warnanya oranye cerah dengan garis-garis hitam di sekelilingnya. Bentuknya mirip bola basket merek-merek terkenal, seperti: Proteam yang dipakai DBL, Molten yang dipakai IBL, dan Spalding yang dipakai NBA. Bedanya, bola yang saya punya itu cepat benjol.
Setiap malam, sehabis dipakai latihan melantun di halaman rumah, saya mengelap bola itu sampai bersih. Saya bahkan pernah tidur sambil memeluk bola. Kata Tsubasa Ozora—tokoh utama dalam komik Captain Tsubasa—bola adalah teman. Dan sebagai seorang teman yang baik, saya tidak bisa membiarkan bola basket saya tidur sendirian.
Tidak sampai seminggu, bola itu kemudian rusak. Benjol parah di mana-mana. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin karena terbuat dari karet murahan. Dan harganya Rp20.000. Jadi, tidak bisa awet sampai lebih dari seminggu.
Karena bola rusak, saya pun terpaksa menabung lagi. Menyisihkan uang Rp1000 setiap hari. Untuk membeli bola basket yang sama. Saya tidak tahu harus beli bola basket ke mana lagi. Hanya bola basket karet itulah satu-satunya harapan saya.
Siklus itu berulang-ulang setiap minggu. Entah sudah ada berapa bola basket yang saya beli saat SD. Entah sudah berapa rupiah pula yang telah saya keluarkan untuk membeli itu. Mungkin kasir Indomaret pun hafal dengan wajah saya karena sering membeli bola di sana. Sampai akhirnya saya berhenti membeli bola basket menjelang SMP. Alasannya sederhana: Saya punya bola basket yang lebih mahal dan tahan lama.
Saya tidak begitu ingat merek bola baru itu. Ayah saya yang membelikannya. Pantulan bolanya lebih mantap. Bahannya awet sehingga tahan berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai permukaannya hampir tidak berbentuk lagi. Garis-garis hitam yang seharusnya ada di sana menghilang pelan-pelan. Aus tergerus lantai semen yang kasar, bahkan tanah yang sedikit berbatu. Sebab, selain di lapangan basket, saya sering melantun bola di halaman rumah—yang kebetulan saat itu—masih berbentuk bidang tanah yang luas.
Sejak SMP kelas delapan, saya hampir tidak pernah membeli bola basket lagi. Alasannya sama sederhana: Saya mulai mengenal toko olahraga. Uang jajan saya juga meningkat. Sehingga saya mampu menabung dan membeli bola basket yang lebih mahal. Saat itu, mahal sama dengan tahan lama.
Begitulah masa kecil saya habiskan. Sampai akhirnya saya benar-benar tidak pernah membeli bola basket lagi. Apalagi SMA saya di Cibadak sudah menyediakan bola sendiri. Saya tinggal datang latihan. Sehingga lupa seperti apa rasanya membeli bola basket.
Ketika dewasa, rasa itu semakin hilang. Jangankan membeli bola basket, bermain basket saja seringkali terlewatkan. Padahal jadwalnya tetap: Setiap Senin di Lapangan DBL Academy. Bersama kelompok Askring alias Asal Keringetan. Namun, tetap saja, kesibukan saya sebagai seorang—katakanlah—jurnalis basket lebih menyita waktu daripada bermain basket itu sendiri.
Oleh karena itu, setiap kali saya melihat anak-anak kecil bermain basket—entah di DBL atau di luar sana—rasanya seperti melihat diri saya di masa lalu. Saya selalu berpikir dan bertanya-tanya: Apakah anak-anak itu membeli bola sendiri? Bola karet yang gampang benjol di mana-mana? Mungkin iya, mungkin juga tidak.
Satu hal yang pasti, ketika melihat anak-anak itu bermain, saya selalu merasa mereka punya kesenangan yang sama dengan saya dulu, yaitu kesenangan bermain basket. Bagaimanapun, basket yang murni hanya ada pada basket anak-anak.
Maka dari itu, saya selalu berdoa—kelak ketika anak-anak itu tumbuh dewasa—mereka bisa menggapai mimpi sebagai seorang penerus bangsa. Yang akan membawa basket kita ke tempat yang lebih baik. Tanpa melupakan betapa senangnya olahraga basket.
Sementara itu, saya—yang bekerja sebagai jurnalis—hanya bisa melanjutkan kisah-kisah mereka melalui tulisan. Meski tingkat minat baca orang-orang Indonesia rendah, saya selalu percaya bahwa tulisan-tulisan inilah yang akan membantu basket kita lebih maju. Kisah-kisah mereka yang berjuang itulah yang akan mendorong perjuangan lainnya.
Tampak naif memang, tetapi—seperti halnya menabung uang untuk membeli bola basket—pekerjaan ini mesti dilakukan sedikit demi sedikit. Dan semoga saja lama-lama menjadi bukit. Sampai tujuan itu sendiri tercapai.
Foto: Dika Kawengian













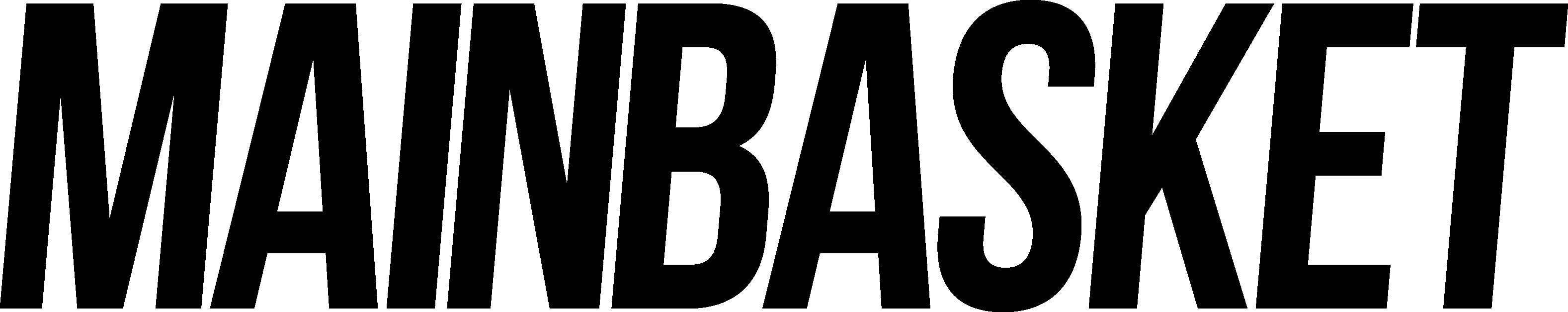




 0822 3356 3502
0822 3356 3502