Olahraga bisa bikin badan kita sehat. Jiwa kita juga kuat. Jadi pengurus olahraga di Indonesia mungkin bisa punya efek berbalik. Badan sakit semua. Lalu sakit jiwa. Wkwkwkwk…
Kebetulan, dalam dua tahun terakhir dunia saya jauh lebih disibukkan dengan dunia olahraga (sebelumnya dunia media). Bila sebelumnya lebih banyak ke olahraga anak muda di arena basket, kemudian banyak di dunia sepak bola.
Ayah saya, yang dulu puluhan tahun berkecimpung di sepak bola, sering tertawa melihat dunia saya yang baru itu. “Dunia kamu sekarang dikelilingi dengan emosi,” katanya lantas tertawa, pada suatu waktu.
Dulu saya mengira, takdir saya adalah di dunia media. Keluarga saya besar di dunia media. Ketika dikirim ikut beasiswa pertukaran pelajar SMA ke Amerika, saya juga ditampung oleh keluarga pemilik media.
Sekarang saya berpikir, jangan-jangan takdir saya memang di dunia olahraga.
Kalau diruntut ke belakang, pekerjaan pertama saya justru di olahraga. Saya memang pernah menjadi pelayan restoran dan barista saat kuliah. Tapi kalau dibilang pekerjaan, itu bukan yang pertama.
Saat masih SMA di Ellinwood, Kansas, saya sebenarnya sudah pernah bekerja dan dapat gaji. Dan itu sebagai pelatih sepak bola!
Kebetulan, di kota itu ada program akhir pekan untuk anak-anak. Salah satunya sepak bola. Setiap sesi dua jam. Rupanya, administratur kota menyadari bahwa ada siswa pertukaran asal Indonesia yang bisa main sepak bola.
Waktu itu, saya memang pernah masuk koran setempat (milik keluarga angkat saya. Ditulis kalau saya suka sepak bola dan bulu tangkis, sempat ikut klub di keduanya. Waktu SD hingga masuk SMP, saya memang pernah ikut sepak bola di Indonesia Muda , serta bulu tangkis di Djarum Surabaya.
Setelah diajak bertemu (interviu?), saya pun diminta jadi pelatih anak-anak SD kelas 1-2. Honornya: 15 dollar (Amerika) per jam. Lumayan untuk pelajar umur 16 tahun di tahun 1993!
Enak sekali mengajar anak-anak SD di Amerika. Nurut-nurut. Tidak pernah terlambat datang. Selalu siap rapi berbaris atau mendengarkan instruksi.
Paling berkesan, setiap usai latihan mereka selalu berteriak minta saya beratraksi: “Rully, Rully, bicycle kick!”
Ya, panggilan saya di Kansas waktu itu adalah “Rully.” Ya, waktu itu saya masih bisa salto (wkwkwkwk…).
Kemudian, di Kansas itu pula saya kenal basket…
***
Dunia saya sekarang memang penuh dengan tantangan. Dunia olahraga di Indonesia ini penuh dengan potensi. Tapi juga bertaburan dengan perangkap.
Tidak ada sejarah panjang pengelolaan yang profesional. Yang ada adalah sejarah panjang olahraga dibina oleh dunia politik dan pemerintahan.
Mau menuju profesional murni? Ada banyak jalan yang bisa dipilih, ada banyak pendapat yang berbeda-beda.
Yang jadi masalah: Masih banyak orang belum paham apa itu profesional murni. Masih terbawa oleh nostalgia “cara lama.” Atau mungkin ingin tetap seperti cara lama?
Jujur, belum ada jalan yang terbukti benar.
Di tengah dunia penuh tantangan ini, saya hanya ingin melakukan apa yang saya percaya baik. Tidak harus paling heboh. Tidak harus paling glamor. Tapi minimal harus paling konsisten. Ibarat dunia lari, jangan berpikir seperti sprint. Harus berpikir seperti maraton.
Pada 2009, saya pernah diminta tolong mengelola liga basket nasional (profesional). Waktu akhirnya saya setuju, liga itu bernama National Basketball League (NBL) Indonesia.
Saya (dan teman-teman di PT DBL Indonesia, serta klub-klub peserta) mencermati apa yang selama ini terjadi, lalu mencoba menjadikan NBL lebih baik dari sebelumnya.
Pada turnamen pramusim pertama di Malang, saya mengajak para pemain dari sepuluh klub peserta untuk duduk bersama di lapangan. Duduk di lantai semua.
Saya sampaikan langsung ke mereka, saya minta maaf. Karena nasib pemain masih prioritas ketiga. Prioritas pertama adalah liga yang sehat. Kalau liganya sehat, maka klub-klubnya akan sehat. Kalau liga dan klubnya sehat, baru pemain akan lebih baik lagi.
Kalau kepada pimpinan/pemilik klub, yang saya tegaskan waktu itu adalah konsistensi dalam penerapan regulasi. Plus, yang sangat-sangat penting: Konsistensi dalam penjadwalan kompetisi.
Saya bersyukur, selama lima tahun menjadi commissioner NBL, basket kita waktu itu berkembang.
Penonton memecahkan rekor. Jadwal juga konsisten. Sebelum babak playoff, jadwal musim selanjutnya sudah ditetapkan bersama. Tidak ada kebingungan soal jadwal.
Jumlah klub bertambah jadi 12. Sponsor klub bertambah. Ada yang mengklaim meraih rekor sponsor tertinggi sepanjang eksistensi klub tersebut. Gaji pemain jauh membaik.
Begitu kontrak lima tahun saya sebagai pengelola berakhir, saya bisa menyerahkan tongkat estafet dengan bangga. Siapa pun yang melanjutkan, dia hanya perlu meneruskan yang selama ini sudah jauh membaik.
***
Tentu saja, sepak bola beda dengan basket. Ini olahraga masyarakat luas. Semakin banyak partisipannya, semakin banyak pula ragam orangnya.
Biasanya, di kolam yang makin besar, partisipan baru akan menemui tantangan ekstra. Karena mayoritas mungkin terbiasa dengan hal-hal lama. Tidak paham dengan cara-cara baru.
Repotnya, yang tidak paham itu bisa sok tahu dan sok benar.
Tidak apa-apa, namanya juga proses. Nikmati saja prosesnya.
Karena partisipasi saya sebagai pengelola klub, maka saya menggunakan acuan yang berbeda dengan sebagai pengelola liga dulu. Bagaimana supaya klub itu bisa benar-benar besar? Bukan sekadar besar nama atau sejarahnya, tapi besar dalam kemampuan menghidupi kelangsungan dirinya sendiri.
Saya penggemar National Football League (NFL). Liga olahraga terbesar di Amerika (American Football). Klub favorit saya sejak SMA: Kansas City Chiefs. Jadi, saya mencoba mengacu pada prinsip yang mereka gunakan untuk mengembangkan diri.
Di NFL, ada tiga jenis equity yang digunakan untuk mengukur besar tidaknya sebuah klub. Kalau salah satu tidak terpenuhi, mungkin klub tersebut tidak layak untuk bertahan.
Pertama,Fan Equity.
Penjelasannya: Seberapa besar kemauan dan kemampuan penggemar klub tersebut dalam menunjang kelangsungan klubnya. Dalam hal ini, kemauan dan kemampuan dalam membeli tiket pertandingan dan merchandise orisinal. Ini salah satu kunci kelangsungan hidup klub tersebut.
Kedua,Social Equity.
Ini relatif baru, karena acuannya adalah seberapa aktif para penggemar klub tersebut dalam berinteraksi di dunia maya. Khususnya di media sosial.
Ketiga,Away Equity.
Yang ketiga ini tidak banyak disadari, tapi punya peran penting apabila sesama klub ingin “bahu-membahu” mengembangkan diri. Away Equity adalah peran sebuah klub dalam membantu mendatangkan pendapatan ekstra bagi lawannya saat pertandingan away.
Tiga equity tersebut sebenarnya sangat sederhana. Kalau tiga itu bisa terpenuhi, barulah sebuah klub bisa dinyatakan besar beneran. Walau sederhana, kalau kita melihat sekeliling di Indonesia, tidak banyak yang benar-benar bisa memenuhi ketiga kriteria tersebut.
Kalau murni profesional, maka ke depannya hanya klub-klub yang bisa memenuhi tiga kriteria itu yang bisa eksis. Karena kalau tiga kriteria itu terpenuhi, lalu organisasinya bekerja secara baik, maka klub itu punya kans untuk mencapai sustainability. Plus mendukung lingkungannya untuk ikut maju.
Terus terang, dan saya kira semua bisa melihat, saat ini sepak bola Indonesia belum seperti itu. Untunglah, ada harapan untuk menuju ke sana. Di mana ada harapan, ke sana kita bisa bergerak.
Semoga saja harapan itu terus terjaga. Potensinya (sangat) ada. Orang banyak yang belum paham. Tapi saya yakin kelak akan paham.
Bagi saya pribadi, dunia yang sekarang ini saya anggap saja seperti kuliah S3 di dunia olahraga. Bedanya dengan kuliah beneran, tidak ada dosen yang bisa membimbing. Hanya hasil akhir yang menjadi penentu kelulusannya.
Semoga saya kelak tetap bisa lulus.(*)
***
Tulisan ini lebih dulu tampil di happywednesday.id

























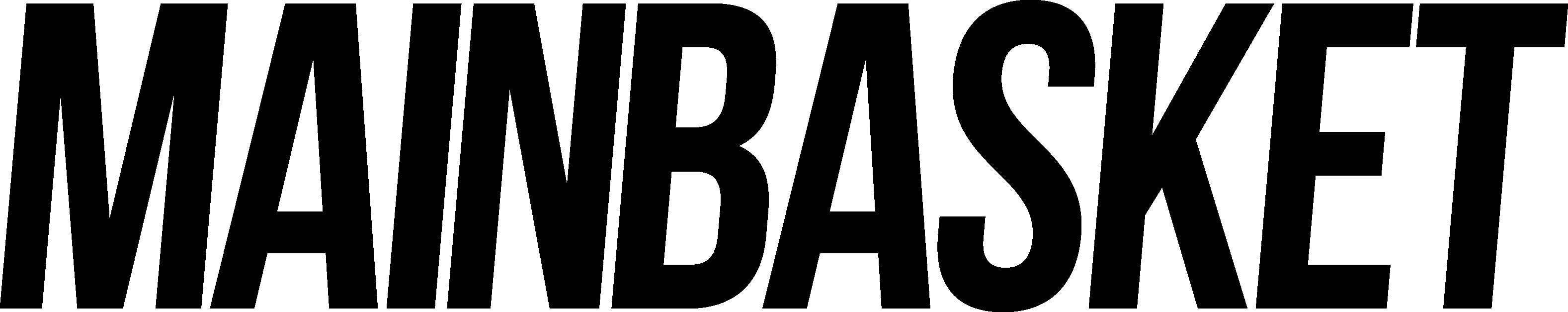




 0822 3356 3502
0822 3356 3502