Kodrat semesta telah membuktikan, bahwa sesuatu yang ada pasti akan tiada, suatu yang gembira pasti kelak akan menghasilkan duka. Sesuatu yang hidup pasti akan menanti kematian.
Saya yakin itu hanya aforisma sembarang yang mungkin tak bisa dibuktikan oleh siapapun. Namun pada dasarnya hidup memang dibubuhi keseimbangan. Maka boleh dibilang, yang abadi hanyalah keseimbangan.
Ironisnya, konteks keseimbangan ini justru kadang terjadi pada waktu yang sekejap, tak berjeda, dan dalam waktu yang bersamaan memunculkan dualisme emosi yang sulit dideskripsikan.
Dan saya yakin, itulah apa yang dirasakan sebagian besar warga kota Minneapolis, Amerika Serikat. Bagaimana tidak, dalam rentang dua hari, dua lonjakan emosi yang bertolak belakang seolah menumbuk sanubari mereka.
Rabu Malam, 20 April waktu bagian Amerika (Kamis pagi waktu Indonesia), akhirnya Minnesota Timberwolves --salah satu klub olahraga yang kerap dianggap paling minim prestasi di kota itu- mengumumkan sebuah kabar gembira untuk menyambut musim NBA berikutnya.
Tom Thibodeau, eks pelatih Chicago Bulls memutuskan untuk berlabuh di Timberwolves. Tidak cuma jadi pelatih, dia juga dimandati oleh Glenn Taylor untuk menjadi president of basketball operation, atau orang yang bertanggung jawab atas kemajuan tim ke depannya.
Thibs, panggilan akrabnya, mengawali karir sebagai asisten pelatih untuk Timberwolves di musim 1989/1990, dan mengarungi belantara kepelatihan, menjadi asisten Doc Rivers ketika ia membawa Boston Celtics juara NBA tahun 2008; hingga prestasi teranyarnya yang berhasil membuat Chicago Bulls selama musim 2010-2015 menjadi tim papan atas NBA.
Di antara pelatih yang masih lowong seperti Mark Jackson, Jeff van Gundy, Scott Brooks, dan Thibs, memang nama Thibs yang paling dianggap berharga. Thibs punya segudang pengalaman, intensi defense yang kuat, dan selalu menolak untuk menyerah tanpa berjuang.
Kabar bergabungnya Thibs ke Timberwolves segera membuat asa para pendukung melambung tinggi. Semua berandai-andai akan jadi seperti apa tim dengan kualitas pemain muda terbaik di NBA ketika dikombinasikan dengan pelatih tangan besi yang haus prestasi. Belum lagi dengan tambahan draft pick musim ini yang tampaknya akan berbuah pemain kelas wahid. Bahan-bahan terbaik untuk racikan sempurna!
Tapi semesta ini adil, warga kota Minneapolis tak diberi waktu lama untuk bersuka ria. Sehari setelahnya, kabar duka terpampang di headline berbagai portal media. Musisi legendaris, Prince meninggal dunia.
Prince adalah produk asli kota Minneapolis. Ia lahir dan meninggal di Minnesota. Ia berkarir selama empat puluh tahun, dari tahun 1976 hingga 2016. Bahkan, kalau boleh jujur, mungkin Prince adalah ikon kota Minneapolis, melebihi siapapun, dalam hal apapun.
Coba bayangkan dampak kultural yang diberikan Prince dari Minneapolis untuk dunia. Ia berhasil membuat semacam sub-genre baru dalam musik yang diberi nama Minneapolis Sound. Sebuah genre musik eksperimental yang menggabungkan musik rock, funk, electric dan new wave. Ya, kurang lebih mirip dengan apa yang didedikasikan Nirvana terhadap kota Seattle sampai dianggap leluhurnya musik Grunge.
Prince sepanjang karirnya berhasil mendapatkan tujuh Grammy Awards, satu Golden Globe Awards, dan satu Academy Awards. Kepergian Prince pastilah membawa banyak duka di penjuru dunia, terlebih lagi kampung halamannya di Minneapolis.
Sungguh, semesta berkerja dengan cara yang tak bisa dimengerti. Baru saja harapan baru dimunculkan lewat kedatangan Tim Thibodeau, seketika akar yang telah jadi identitas Minneapolis dicabut lewat kepergian Prince.
Tapi, saya rasa memang sedari awal, semesta telah menyimpan rencana tak terduga buat Minneapolis. Tahun lalu kedatangan Karl Anthony Towns ditandai dengan kepergian Phil Saunders.
Lantas apalagi rahasia semesta yang tengah dibentangkan untuk kota Minneapolis? Kita tunggu saja.
(Minnesota adalah state/negara bagian, Minneapolis adalah kota terbesar di Minnesota)
Foto: CNN/GettyImages























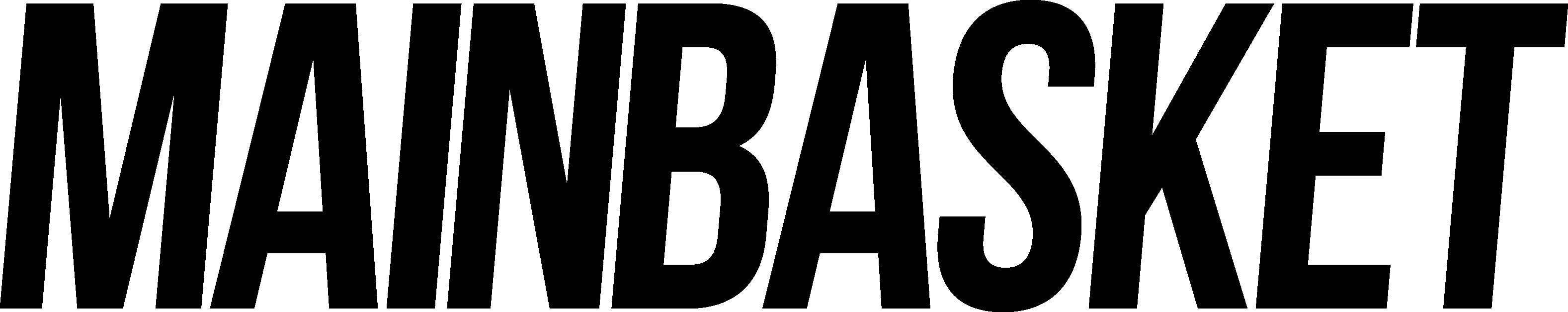




 0822 3356 3502
0822 3356 3502