Orang bilang, janganlah mencampuradukan olahraga dengan politik. Akan tetapi, toh, pada akhirnya pilihan untuk tidak berpolitik sebenarnya politik. Mereka yang mengaku golongan putih (golput) dalam pemilihan umum adalah orang-orang yang juga berpolitik. Mereka memilih untuk tidak memilih. Itu pilihan politik yang keabsenannya tetap ikut menyumbang terbentuknya suatu hal di kemudian hari.
Ini jadinya seperti kalimat terkenal di ranah komunikasi: “we can not not to communicate” (kita tidak bisa tidak berkomunikasi)—maka, kita juga tidak bisa tidak berpolitik.
Bahkan di tahun-tahun terakhir ini, terutama menjelang pemilihan presiden 2019, sudah banyak orang menyadari bahwa politik adalah hal yang melekat dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak, politik mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Orang-orang kadang hanya salah mengartikan politik. Mereka memandang politik sebagai sesuatu yang negatif, jahat, dan menyakiti tanpa mau mengenal apa itu politik.
Padahal, menurut pandangan klasik Aristoteles, politik adalah suatu usaha warga negara dalam membicarakan dan menyelenggarakan hal-hal yang menyangkut kebaikan bersama. Ia juga mengatakan, manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikatnya sebagai warga negara untuk hidup dalam polis (city-state atau negara).
Di ranah basket, bolehlah kita menyebut NBA sebagai polis tadi, tetapi dengan lingkup yang lebih kecil. Mereka bisa menjadi sebesar sekarang pun bukan karena sulap atau sihir, tetapi berkat berbagai hal yang mendukungnya, termasuk—tentu saja—politik.
Intinya, di mana persoalan itu menyangkut hajat banyak orang, di situlah politik akan ada. Begitu pun di ranah basket yang tentu saja melibatkan sedemikian banyak orang. Itu sudah pasti dan lumrah, sebenarnya.
Lihat saja NBA ketika memindahkan NBA All-Star Game 2017 dari Charlotte ke New Orleans. Saat itu mereka memindahkan acara karena tidak sreg dengan kebijakan negara bagian North Carolina yang dianggap mendiskriminasi lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer (LGBTQ).
Apa itu namanya kalau bukan politik? Gubernur North Carolina Pat McCrory bahkan mengatakan keputusan NBA sebagai “another classic example of politically correct hypocrisy gone mad”—Politik!
Nah, kini ketika McCrory tidak lagi menjabat sebagai gubernur—meski Donald Trump yang sama-sama dari Partai Republik memenangkan pemilihan umum—suksesornya, Roy Cooper, berjanji mengubah kebijakan sehingga NBA mau menggelar All-Star Game 2019 di North Carolina. Maka, pada titik ini, kita bisa melihat sejauh mana NBA terlibat dalam membentuk kebijakan baru yang mendorong suatu negara bagian mengubah aturannya demi mendongrak reputasi nasional bahkan dunia.
Itu politik!
Contoh kasus lain: NBA kini mengubah aturan warna sepatu pada 2018-2019 yang membuat para pemainnya bebas mengenakan sepatu berwarna apa saja. Dengan kebijakan baru itu, merek-merek terkenal seperti Nike, Jordan, adidas, Under Armour dan lain-lain beserta para ambasadornya jadi lebih mudah untuk berkreasi. Mereka memiliki kesempatan untuk semakin membesarkan dunia sepatu dengan desain yang—selain fungsional—juga atraktif dan bernilai jual tinggi.
Para pemain ruki (rookie) dan sophomore yang menjadi ambasador Nike, seperti Jayson Tatum (Boston Celtics) dan Luka Doncic (Dallas Mavericks), misalnya, segera merespon perubahan aturan itu dengan menciptakan kreasi sepatu berwarna-warni sarat makna pada September 2018. Mereka lalu mengenakan sepatu itu di pertandingan pembuka NBA 2018-2019 yang membuat lapangan lebih berwarna. Lantas, apa artinya perubahan aturan itu kalau tidak ada singgungannya dengan politik? Bagaimanapun, dengan perubahan aturan itu, NBA dan para pegiat di sekitarnya menjadi lebih mudah “menjual” nama mereka sebagai salah satu kompetisi, komoditas, sekaligus merek besar yang mendatangkan berbagai keuntungan.
Ini, kan, persis seperti pandangan klasik Aristoteles tadi tentang hal-hal yang menyangkut kebaikan bersama.
Kendati demikian, kerangka berpikir itu juga tidak melulu bisa diterima semua orang. Masih ada beberapa orang yang menganggap olahraga—dalam hal ini adalah basket—harus jauh-jauh dari politik dan hal lainnya. Kita mesti membicarakan basket sebagai basket tanpa memasukkan unsur apa pun dalam permainan itu. Kita seolah mesti mencabut semua hal di luar basket untuk membahas basket itu sendiri. Padahal sebenarnya urusannya tidak sesederhana itu. Basket memang olahraga permainan, tetapi seperti yang saya katakan: ia besar karena banyak hal. Basket bahkan bisa menjelma cerita yang tidak bisa dijelaskan hanya dalam bingkai empat kuarter.
Lagi pula mengapa kita harus begitu anti-politik di ranah olahraga? Apakah semua induk olahraga, misalnya, harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpolitik? Rasanya akan sulit mencari orang yang tidak berpolitik mengingat hakikat kita sebagai seorang manusia yang sulit menghindar dari hal itu.
Anehnya, beberapa orang bahkan ada yang bilang, jika orang politik memegang kekuasan dalam induk olahraga, hasilnya tidak akan bagus. Sebuah induk akan hancur jika orang-orang politik yang mengurusnya. Maka, solusinya, orang-orang yang mengerti basketlah yang harus mengambil alih kerja induk olahraga tersebut. Padahal sebuah induk tampak hancur-hancuran bukan terjadi karena politik itu sendiri, tetapi justru karena para pelakunya yang tidak kompeten.
Hans Kelsen, seorang filsuf abad 20-an, menyebut politik memiliki dua arit dalam praktiknya. Pertama, sebagai etik yang berkenaan dengan tujuan manusia agar tetap hidup sempurna. Kedua, sebagai teknik yang berkenaan dengan cara manusia mencapai tujuannya. Jika suatu induk yang tadi dibicarakan tampak hancur-hancuran, ada kemungkinan para pelakunya menggunakan politik dengan etik dan teknik yang salah kaprah. Mereka mengurus sebuah persoalan bukan untuk kebaikan bersama melainkan kebaikan pribadi atau golongannya.
Itulah yang terjadi selama ini sehingga sebagian dari kita memandang politik itu jahat. Padahal politik tidak melulu bekerja seperti itu.
Sekarang, coba pikirkan: apakah induk basket di Indonesia, yang dipegang oleh orang yang mengerti basket, saat ini sudah bagus? Di mana posisi basket kita dibandingkan yang lainnya, setidaknya di Asia Tenggara? Bukankah (tim nasional) kita masih kalah dari Filipina karena basket kita mentok di situ-situ saja? Lantas, mengapa kita harus terus menerus mengatakan orang-orang politik harus menjauh dari induk seperti ini, sementara orang yang mengerti basket saja tidak tahu apa yang sedang ia lakukan?
NBA, kan, dipegang Adam Silver yang memiliki latar belakang hukum dan seorang Demokrat, bukan seorang bekas pemain, pelatih, atau apa pun yang berkaitan dengan basket. Lah, kok bisa NBA sebesar itu di tangan seorang politikus?
Kalau sudah begini, kita mau bilang apa?
Foto: NBA













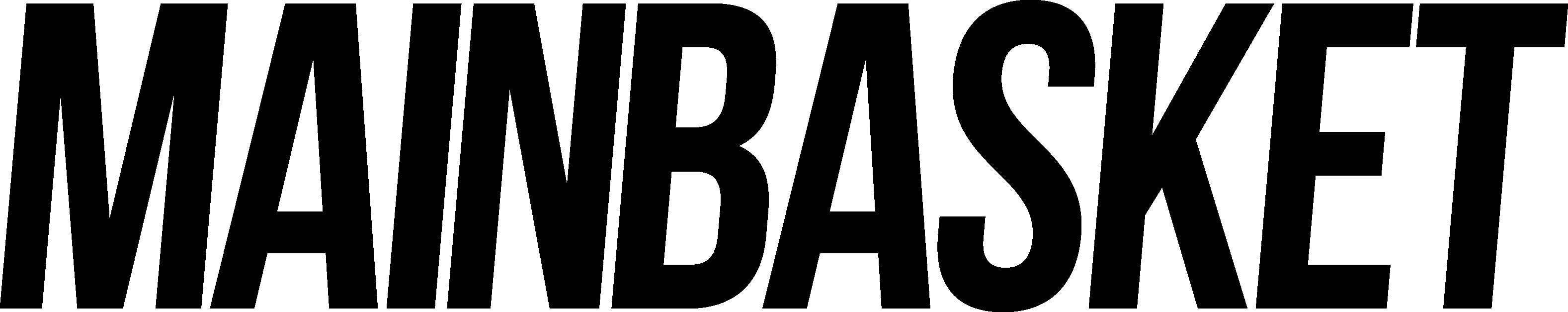




 0822 3356 3502
0822 3356 3502