Ditulis oleh: Louise Dewangga
Masyarakat Serbia begitu gandrung mengenai olahraga. Tidak hanya gandrung mereka juga total mendukung tim yang mereka cintai. Judul lagu, “There is A Light That Never Goes Out”, milik band legendaris Inggris, The Smiths, rasanya cocok menggambarkan romantisasi olahraga masyarakat Serbia. Utamanya bagian, “To die by your side, it's such heavenly way to die," tampaknya benar-benar diimani oleh masyarakat Serbia untuk mendukung total tim kebanggaan mereka.
Dalam prosesnya, ada dua tim yang memiliki basis penggemar besar. Kedua tim itu adalah Red Star dan Partizan. Tak sekadar bersaing di lapangan, kedua klub tersebut memiliki akar sejarah serta pemahaman yang bertolak belakang, yang membuat persaingan keduanya semakin dalam.
Red Star menjadi salah satu klub tersukses di Serbia pada era 1990-an. Bukan hanya menjadi klub sukses saja. Red Star juga menjadi kendaraan bangkitnya nasionalisme masyarakat Serbia.
Slobodan Milosevic, ketua Partai Komunis Serbia mendapat popularitas dan kekuasaannya dengan menguliti nasionalisme bangsa Serbia yang telah lama tertindas. Salah satu contohnya adalah stadion klub Red Star. Pendukung Red Star kerap membawa plakat-plakat bergambar wajah-wajah santo Gereja Ortodoks dan novelis ultranasionalis Vuk Draskovic.
Di setiap laganya, mereka juga meneriakkan yel-yel dengan kalimat, “Serbia, bukan Yugoslavia”. Sejak awal Red Star memang menjadi benteng nasionalisme. Mengingat akar klub ini yang dibentuk oleh Gerakan antifasis Yugoslavia pada era 1945. Di bawah rezim komunis, klub-klub Eropa Timur pada dasarnya megikuti model patronasi yang sama.
Biasanya, sebuah klub olahraga didirikan dan disokong oleh tentara, klub lain disantuni oleh polisi, yang lain lagi bersekutu dengan serikat-serikat dagang dan kementerian. Di Belgrade, polisi mendukung Red Star sementara tentara menyokong Partizan.
Sampai sini rasanya kita bisa memahami mengapa rivalitas atau bahkan tensi panas dari kedua pihak terus meninggi. Di lain sisi, bagi para nasionalis Serbia, tentara melambangkan musuh dari cita-cita mereka. Ideologi tentara komunis menolak gagasan identitas separatis Serbia.
Mereka membunuh, memenjarakan, bahkan menindas Gereja Ortodoks Serbia. Dengan musuh yang sedemikan pelik, Red Star menjadi wadah bagi warga Serbia yang bercita-cita merebut kembali martabat bangsanya.
Berbeda dengan Red Star, Partizan identik dengan klub yang lebih dekat dengan pemerintah Yugoslavia. Bahkan Partizan mengubah warna besar klubnya yang sebelumnya berwarna merah biru ke warna hitam putih khas Yugoslavia. Mantan pemimpin kelompok suporter Partizan, Franjo Tudjman, menjadi presiden Kroasia pertama pada 1991.
Penggemar Red Star sering melabeli dirinya sebagai agen perubahan politik. Memang benar, di awal tahun 2000 bersama dengan penggemar Partizan mereka meninggalkan pertandingan hanya untuk menggulingkan tirani Milosevic. Kejadian ini disebut juga dengan "Revolusi Red Star."
%20(16).jpg)
David Goldblatt salah satu penulis asal Amerika Serikat pernah berujar bahwa Serbia menjadi negara dengan kondisi olahraga yang mengesankan. Antusiasme dan fanatisme masyarakat Serbia, terutama Kota Belgrade begitu tinggi.
Hal ini juga tak terkecuali dengan olahraga basket di Belgrade. Bahkan penggemar Red Star satu pemahaman dengan manajemen untuk tidak mengontrak mantan pemain Serbia yang sebelumnya bermain untuk Partizan Belgrade.
Peraturan ini sejatinya sudah terimplementasikan pada kasus tim sepak bola Red Star. Kini tim basket mereka mengaplikasikannya dengan pengecualian khusus. Seperti pemain lokal yang bermain untuk tim senior Partizan tidak akan pernah berseragam Red Star. Pemain asing mendapat pengecualian dengan syarat pertimbangan yang pelik.
Salah satu bintang jebolan Partizan Belgrade adalah Bogdan Bogdanovic yang saat ini berseragam Atalanta Hawks. Sebaliknya Red Star menjadi satu-satunya klub di dunia yang dua pemainnya masuk dalam jajaran Hall of Fame FIBA (Stankovic dan Nikolic).

Derbi keduanya memang selalu ditunggu dan wajib untuk diabadikan. Baik Red Star maupun Partizan sama-sama menjadi jawara basket di Serbia. Kemenangan dan trofi hanyalah bonus semata. Harga diri dan ideologi yang mereka pegang dan tanam sejak beberapa dekade ke belakang akan tetap mereka bawa ketika melantunkan bola di lapangan.
Jauh dari Serbia, di Indonesia sendiri dirasa sedikit susah untuk membangun animo serupa. Multiklub olahraga rasanya masih sedikit dijumpai di sini. Terlebih lagi basket Indonesia yang terpaku ke Amerika Serikat juga membentuk budaya persaingan dan menonton yang bertolak belakang dengan klub-klub liga Eropa yang begitu fanatik. Sebenarnya bisa, mengingat masyarakat Indonesia masih memiliki rasa cinta kedaerahan mereka.
Pada awal munculnya klub-klub baru seperti Bumi Borneo, banyak orang mengomentari kemunculan klub ini dengan ujaran akhirnya ada perwakilan Pulau Kalimantan di liga basket tertinggi, IBL. Atau paling terbaru berubahnya Dewa United Banten yang sebelumnya Dewa United Surabaya. Banyak orang menyayangkan karena klub yang membawa nama Surabaya di IBL kini hanya tersisa Elang Pacific Caesar Surabaya.
Jelas jika ingin membangun hal serupa memakan waktu yang bukan hanya satu atau dua malam saja. Kembali lagi, itu semua hanyalah sebuah harapan yang entah kapan bisa terwujud. Mengambil contoh yang baik entah dari Amerika Serikat atau dari klub-klub Liga Eropa tidak menjadi masalah jika tujuan utamanya membuat basket Indonesia menjadi jawara dunia. Ada amin?(*)
Foto: EuroLeague

























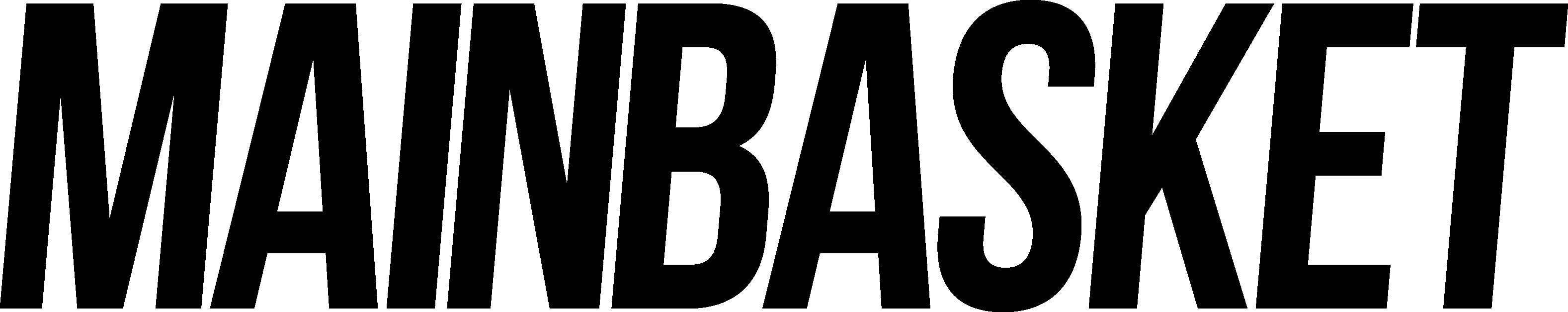




 0822 3356 3502
0822 3356 3502